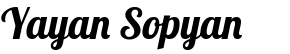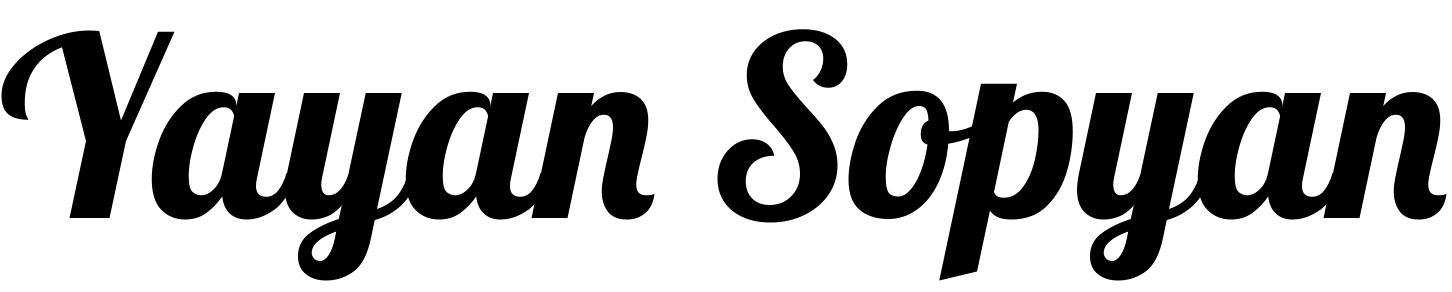Suatu hari seorang teman berkata, ia menyukai novel seorang penulis perempuan, sebut saja bernama R. R adalah salah seorang penulis berlatarbelakang akademis yang kental dengan novel-novel yang kerap menjadi best seller.
Kenapa? tanya saya.
Iya, saya suka karyanya. Gaya bahasanya memang membingungkan, tapi itulah ciri khasnya, jawab teman tadi lugas.
Sekarang, giliran saya yang jadi bingung. Saya baru tahu bahwa membingungkan kini masuk daftar perbendaharaan gaya bahasa kekinian kita. Yang lebih membikin bingung, gaya itu bisa dianggap sebagai ciri khas dan malah disukai pembaca.
Karena penasaran, saya bertanya pada seorang rekan editor yang pernah beberapa kali mengedit buku dari penulis yang sama. Ketika sebuah buku sudah terbit tentu ada peranan editor yang tak bisa dinafikan. Editor bisa dikategorikan pembaca pertama yang pastinya sudah mendeteksi kalau-kalau ada keanehan di dalam sebuah naskah.
Jawaban rekan editor itu ternyata mengejutkan. Gue juga bingung bacanya. Nggak ngerti! Pokoknya tugas gue cuma ngedit semampu yang gue bisa.
Lho? Bagaimana bisa begitu?
Naskah-naskah yang membingungkan itu tak hanya milik penulis di atas. Mereka beredar di sekitar kita. Kita bisa menemukannya di mana saja, toko buku, majalah, koran, ataupun milis. Diksi yang dipilih rumit, meski sebetulnya masih ada pilihan kata yang lebih sederhana. Seolah tingkat kesulitan kata yang dipilih mencerminkan kecemerlangan sebuah gagasan. Padahal penulis bisa memilih diksi yang bagus tanpa harus membuat bingung pembaca.
Namun dari kasus di atas, saya melihat mata rantai bagi kebingungan ini justru sudah tercipta. Ada penulis dengan gaya bahasa membingungkan, editor yang ikut bingung, penerbit yang tetap menerbitkan karya membingungkan, dan pembaca yang senang dibuat bingung. Klop kan?
Tapi saya masih bingung.
Dalil yang pernah saya peroleh sebagai mantan mahasiswa komunikasi menyebutkan, komunikasi adalah persoalan pertukaran makna, bukan semata pertukaran pesan. Kita sebagai komunikator dianggap gagal total apabila komunikan kita tak memahami inti gagasan yang hendak kita sampaikan. Kalau sudah tak paham, boro-boro bisa suka. Apa iya doktrin komunikasi yang saya pegang teguh itu sudah berubah? Jangan-jangan prinsip yang berlaku sekarang, kalau kau tidak bisa meyakinkan pembacamu, buatlah mereka bingung!
Dalam suatu kesempatan kolumnis Mohamad Sobary pernah berujar mengenai cara menulis, ''Ra sah ndakik-ndakik (Tak usah yang aneh-aneh). Banyak dosen yang kalau menulis mbulet menggunakan istilah aneh-aneh. Seolah-olah kalau tidak menyukarkan orang, khawatir tak dianggap sebagai dosen yang pinter,'' sindirnya.
Menurut pendapat dia, untuk menjadi penulis bagus, tak perlu bergaya dengan istilah asing yang terlampau mengharu biru tulisan. Bisa-bisa, ujar Sobary, orang malah menjadi pusing jika membaca tulisan yang disesaki istilah-istilah yang tak familiar di mata pembaca.
Yayan Sopyan, penulis dan pengasuh sebuah sekolah menulis, menggelari tulisan seperti itu sebagai sastra kamus. Maksud dia, sastra yang untuk membacanya memaksa orang membuka kamus lantaran penuh istilah ajaib dan sulit. Ia menangkap kesan kuat bahwa kebanyakan naskah yang semacam itu ditulis dengan semangat menemukan dan merangkai kata-kata yang tidak lazim sebagai bagian terpenting dari kosmetika karya tulis.
Masalahnya, saya rasa kesalahan tidak sepenuhnya bisa kita hujamkan pada penulis yang suka ndakik-ndakik itu. Mereka bisa bilang, wong saya bikin tulisan seperti itu ada media massa yang mau muat. Sudah itu laku dijual kepada penerbit. Memangnya penerbit atau redaktur media massa bodoh ?
Baik penulis, redaktur, dan penerbit pasti akan berkata: akhirnya semua kami kembalikan kepada pembaca. Kalau karya yang membingungkan bisa best seller, wajar saja jika penerbit tetap menerbitkannya. Meskipun hanya untuk membacanya saja editornya sampai kelimpungan.
Kita semua sebagai pembaca bisa dikatakan bertanggung jawab turut melestarikan penulis yang bergaya bahasa membingungkan. Yang lebih berbahaya jika kita menciptakan penulis-penulis baru dengan gaya yang sama, sebab mereka belajar dari penulis terdahulu yang terkenal justru karena berciri khas membingungkan.
Menurut saya, ini bukan semata pada persoalan kurang kritisnya pembaca dalam memahami teks. Kemungkinan besar inti persoalan terletak pada perasaan rendah diri yang pernah menghinggapi setiap kita dengan derajat yang bervariasi.
Jujur saja. Kita seringkali silau dengan atribut-atribut yang dikenakan penulis. Jika si penulis misalnya bergelar doktor, psikolog atau dokter belum apa-apa kita sudah minder.
Buku atau teks saat ini tak lagi sarana komunikasi yang telanjang, yang menghadirkan dirinya secara sederhana. Ia bukan lagi semata wadah untuk menyampaikan makna, tapi menghantarkan citra.
Ketika seorang penulis menghampiri kita dengan segenap atribut -- gelar, jabatan, peran sosial -- yang dimilikinya, persepsi di kepala kita terbentuk. Ia hebat, maka apa yang disampaikannya pastilah hebat pula. Apalagi jika bukunya memperoleh endorsement dari orang-orang terkenal. Makin yakinlah kita akan kehebatan sang penulis.
Bahkan ketika tulisannya penuh dengan kosa kata yang saya tidak mengerti, kita malah berpikir: itulah tanda bahwa dia pintar. Kalau saya tidak paham, mungkin saya yang bodoh. Lalu karena saya ingin dikategorikan pintar, saya pun merasa harus menyukai tulisan itu.
Biasanya hal serupa itu mudah menular. Jika tokoh-tokoh publik saja sudah bisa memberikan pujian setinggi langit melalui endorsement yang diberikannya, masa iya kita berpikiran sebaliknya? Jika banyak orang menilai karya itu bagus, jarang-jarang ada yang berdiri dan menyatakan pendapat yang berlawanan. Kita cemas menjadi berbeda. Kita meragukan diri kita.
Rasanya, sebagai pembaca, kita perlu lebih percaya diri. Kalau setelah membaca sebuah teks kita tak mampu menyimpulkan isinya dalam bahasa kita sendiri, jangan mendadak sontak menyalahkan pikiran kita. Bisa jadi itu salah satu indikator gagalnya penulis menyampaikan pokok pikirannya. Pada saat kita mengatakan kita menyukai karya seorang penulis, pastikan bahwa itu kita lakukan karena kita memahaminya, bukan karena itu membingungkan kita.
Ujian bagi seorang penulis adalah ketika ia bisa secara mahir menyampaikan ide -- serumit apapun itu -- ke dalam bahasa yang mudah dimengerti sebanyak mungkin orang. Bukan sebaliknya, membuat bahasa yang sulit dimengerti agar gagasannya dianggap luar biasa.
Tulisan masihlah bertujuan menyampaikan makna, bukan semata citra. Inilah prinsip komunikasi yang sederhana. Dan sejati.
***
Feby Indirani, pembaca yang tak ingin dibuat bingung
(Dikutip dari Koran Tempo Edisi 25 Februari 2007)