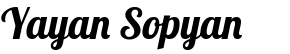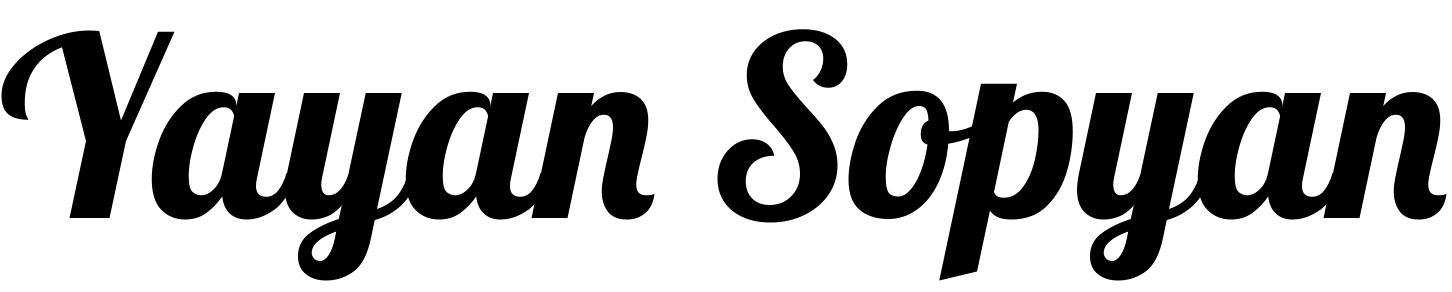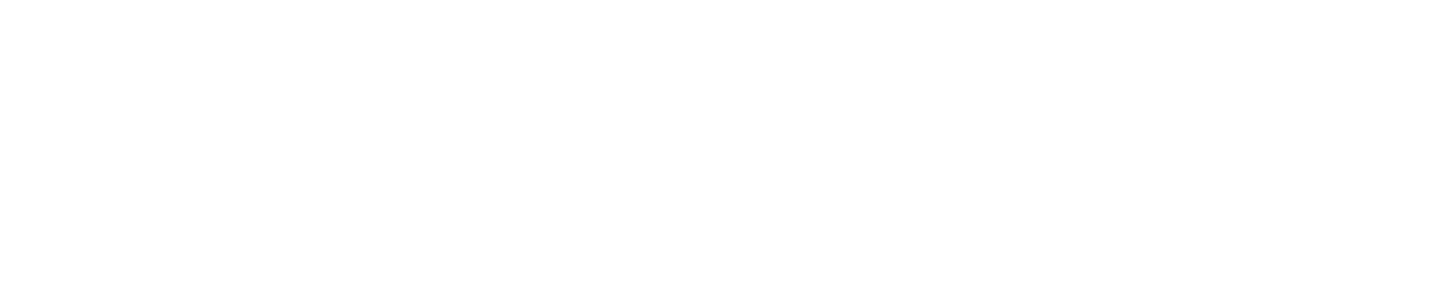Seorang seniman tentu memahami bahwa karyanya akan ditafsirkan dengan berbagai cara. Namun, ketika tafsir itu berujung pada panggilan dari aparat, pertanyaannya bukan lagi soal makna seni, melainkan soal kekuasaan.
Pola ini bukan baru. Dari waktu ke waktu, dari satu negara ke negara lain, seni yang berbicara terlalu lantang kerap dihadapkan pada respons yang lebih besar dari substansi kritiknya sendiri.
Sukatani, band punk dari Purbalingga, minggu ini menyampaikan permohonan maaf atas lagu Bayar Bayar Bayar—sebuah lagu yang mengkritik praktik korupsi dan suap di kalangan polisi negeri ini. Lagu itu semakin viral setelah menjadi nyanyian yang terus berkumandang dalam aksi demonstrasi mahasiswa bertema "Indonesia Gelap" sepanjang pekan lalu.
Punk bukan sekadar genre musik, tetapi tradisi perlawanan yang menolak tunduk pada kekuasaan. Kalau kita mengesampingkan kemungkinan adanya tekanan yang sangat besar, maka sulit membayangkan sebuah band punk meminta maaf atas lagu yang justru lahir dari semangat perlawanan.
Belakangan polisi mengaku cuma meminta klarifikasi kepada Sukatani atas lagu itu. Mereka ingin tahu maksud dan tujuan dari lagu yang sekarang begitu viral itu. Sebuah keinginan yang terdengar aneh mengingat posisi sosial pemusik dan liriknya yang sangat mudah dipahami: kritik sosial.
Gampangnya, klarifikasi adalah usaha untuk mendapatkan kejelasan. Dalam komunikasi sehari-hari, kita meminta klarifikasi untuk menghindari kesalahpahaman.
Namun, dalam konteks politik dan hukum, klarifikasi bisa punya makna yang lebih kompleks—dan sering kali berbahaya. Di tangan otoritas, klarifikasi bisa berubah menjadi instrumen untuk menekan pihak yang bersuara. Sebuah pertanyaan sederhana bisa menjadi pintu masuk untuk mengawasi, mengintimidasi, atau bahkan mengekang kebebasan berbicara.
Sukatani mungkin cuma diminta menjelaskan maksud dari lirik lagu mereka. Tapi pertanyaannya, apakah permintaan klarifikasi ini benar-benar untuk memahami, ataukah justru bentuk lain dari tekanan yang lebih halus?
Sering kali, permintaan klarifikasi bukanlah ajakan untuk berdialog, melainkan isyarat bahwa mereka sedang mengawasi. Sensor semacam ini tidak membutuhkan larangan eksplisit—cukup dengan menciptakan atmosfer ketakutan. Ada garis tipis antara permintaan penjelasan dan upaya untuk membungkam suara yang dianggap mengganggu.
Tapi kenapa sebuah lagu bisa dianggap lebih berbahaya daripada laporan investigasi panjang? Jawabannya ada pada cara seni bekerja—ia tidak cuma berbicara kepada akal, tetapi juga menggugah hati.
Berbeda dengan tulisan akademik atau berita yang berisi angka dan data, seni bekerja dalam bahasa emosi. Ia langsung menyentuh kesadaran orang, membuat mereka merasa, bukan sekadar berpikir.
Itulah sebabnya lagu, puisi, atau gambar bisa menyebar lebih cepat dan lebih luas dibanding laporan panjang tentang korupsi. Dan karena itulah, otoritas yang korup lebih takut terhadap seniman dibanding akademisi. Mereka tahu bahwa seni tidak cuma berbicara kepada akal, tetapi juga menggugah hati.
Di dunia ideal, kritik terhadap suatu institusi seharusnya direspons dengan introspeksi dan perbaikan. Tetapi kenyataan sering kali berjalan terbalik. Alih-alih membersihkan tubuh mereka dari korupsi, banyak institusi justru lebih sibuk memoles citra mereka. Daripada membenahi kesalahan, mereka lebih memilih membungkam mereka yang mengungkapkannya.
Dalam logika represi, kritik eksternal selalu dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai umpan balik yang bernilai. Ini adalah bentuk paranoia institusional—ketakutan akan hilangnya kontrol atas narasi. Ketika sebuah lagu punk mendapat perhatian luas, otoritas mungkin tidak takut pada liriknya, tetapi pada dampaknya. Mereka tahu bahwa suara yang tumbuh di luar kendali mereka bisa berubah menjadi gelombang yang sulit dihentikan.
Ironinya, semakin keras sebuah kritik ditindak, semakin besar dampaknya. Grup musik punk yang awalnya mungkin cuma didengar oleh komunitas pecinta musik punk, kini diperbincangkan oleh lebih banyak orang. Permintaan klarifikasi justru membuat lagu mereka lebih dikenal, dan pesan mereka semakin relevan.
Sejarah menunjukkan bahwa setiap kali sebuah karya seni ditekan, ia justru semakin kuat. Larangan sering kali justru menciptakan daya tarik yang lebih besar. Ini adalah efek Streisand—di mana upaya untuk menyembunyikan sesuatu justru membuatnya semakin terlihat. Otoritas yang berusaha mengendalikan narasi sering kali lupa bahwa tindakan mereka sendiri bisa memperkuat kritik yang ingin mereka bungkam.
Mungkin, yang sebenarnya perlu klarifikasi bukanlah seniman, tetapi institusi yang mereka kritik. Kalau sebuah lagu dianggap mengganggu, bukankah lebih baik bertanya mengapa kritik itu muncul daripada mempertanyakan mereka yang menyanyikannya?
Sebuah lagu bisa dilarang, seorang seniman bisa ditekan, tetapi pesan yang sudah tersebar sulit untuk ditarik kembali. Karena pada akhirnya, seni tidak hidup dalam catatan polisi, melainkan dalam ingatan orang-orang yang mendengarkannya.
Dan itulah kekuatan sejati dari seni: ia tidak butuh izin untuk tetap berlanjut.
Pertama kali terbit di Arina.id