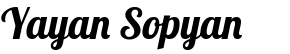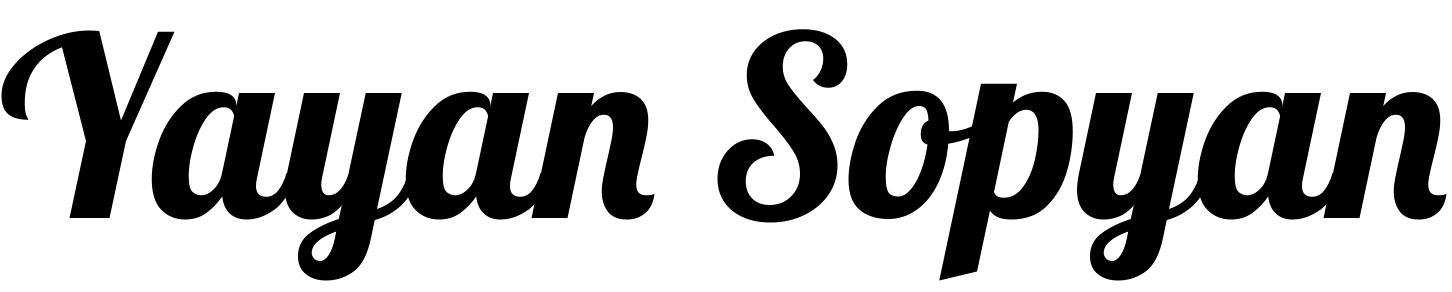Hampir di setiap presentasi tentang artificial intelligence (AI), selalu ada bagian optimis yang menyatakan bahwa meskipun akan menggantikan banyak pekerjaan, AI juga akan menciptakan peluang baru—asal kita mau beradaptasi.
Kemudian, frasa yang paling sering muncul? Reskilling. Orang didorong untuk belajar keterampilan baru yang terkait dengan AI, untuk mendapatkan pekerjaan baru setelah ia kehilangan pekerjaan lama gara-gara AI.
Laporan terbaru dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) memperkirakan bahwa 40 persen pekerjaan di dunia akan terdampak oleh AI. Berbeda dengan gelombang otomatisasi sebelumnya yang menghantam sektor manufaktur, kali ini AI menyasar pekerjaan berbasis pengetahuan.
Itu berarti pekerja kerah putih—mereka yang dulu merasa aman dari risiko otomatisasi—sekarang ikut terancam. Dan solusi yang ditawarkan, lagi-lagi: reskilling.
Seolah-olah masalah kehilangan pekerjaan bisa diselesaikan seperti mengganti baterai remote: tinggal dibuka, diganti, dan semuanya kembali normal. Tapi benarkah reskilling merupakan solusi nyata? Atau justru menjadi semacam narasi pelarian yang menutupi masalah yang lebih struktural?
Gagasan reskilling terdengar inklusif dan memberi harapan. Gagasan itu menyiratkan bahwa siapa pun, dari tukang las sampai pegawai bank, bisa tetap relevan selagi mau belajar hal baru. Tapi ketika kita lihat lebih dekat, pertanyaan besar muncul: siapakah yang benar-benar bisa menjalani proses reskilling ini?
Sebagian besar orang bekerja bukan karena mereka sedang menapaki karier impian. Mereka bekerja karena harus menyambung hidup. Mereka bekerja dalam jam panjang, dan sering kali tanpa jaminan sosial yang memadai.
Ketika diminta reskilling, artinya mereka harus punya waktu ekstra, uang untuk ikut pelatihan, koneksi internet yang stabil, dan literasi digital yang cukup. Ini bukan hal remeh. Dalam banyak kasus, reskilling adalah kemewahan yang tidak tersedia bagi mayoritas.
UNCTAD sendiri mengakui adanya ketimpangan global dalam kesiapan menghadapi revolusi AI. Infrastruktur digital, lembaga pelatihan, dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi sangat terkonsentrasi di negara-negara maju.
Sementara itu, sebagian besar negara Global South bukan cuma tertinggal dari sisi teknologi, tapi juga tidak diikutsertakan dalam perumusan kebijakan global tentang AI. Akibatnya, mereka tidak cuma menjadi pasar bagi produk AI, tetapi juga ladang eksperimen dan zona terdampak tanpa daya tawar.
Di sinilah reskilling berubah, dari solusi menjadi semacam mitos meritokrasi baru. Alih-alih bertanya bagaimana sistem bisa melindungi mereka yang paling rentan, kita justru menyuruh individu “beradaptasi” agar tidak tertinggal. Gagal mengikuti pelatihan? Salahmu sendiri. Tidak sanggup pindah profesi? Kurang gigih.
Dalam logika ini, kegagalan bukan kesalahan sistem yang tidak memberikan akses, tapi kesalahan personal karena tidak cukup cepat belajar ulang. Padahal yang lebih layak dipertanyakan adalah: mengapa beban perubahan selalu diletakkan di pundak orang-orang yang paling tidak berdaya?
Sementara itu, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari narasi reskilling ini? Korporasi-korporasi raksasa yang terus memacu adopsi AI demi efisiensi dan keuntungan. Pemerintah yang lebih suka bicara tentang “transformasi digital” daripada memperkuat jaring pengaman sosial.
Dalam banyak kasus, reskilling hanyalah kosmetik politik: membuat seolah-olah ada tanggapan terhadap disrupsi, padahal pada kenyataannya sistem tetap membiarkan banyak orang terbuang dari proses.
Kita tidak bisa terus-terusan bicara soal masa depan kerja seakan-akan semua orang memulai dari garis start yang sama. Keadilan digital bukan tentang siapa yang paling cepat beradaptasi, tapi tentang siapa yang punya akses untuk ikut serta dalam proses adaptasi itu.
AI mungkin akan mengguncang cara kita bekerja, tapi dampak guncangan itu tidak perlu menghancurkan hidup manusia—asal kita punya keberanian untuk merombak sistem, bukan sekadar menyuruh orang menyesuaikan diri dengan sistem yang sudah usang.
Bukan AI yang membuat orang takut. Tapi sistem yang tidak memberi ruang untuk bertahan—itulah yang benar-benar menakutkan.