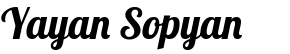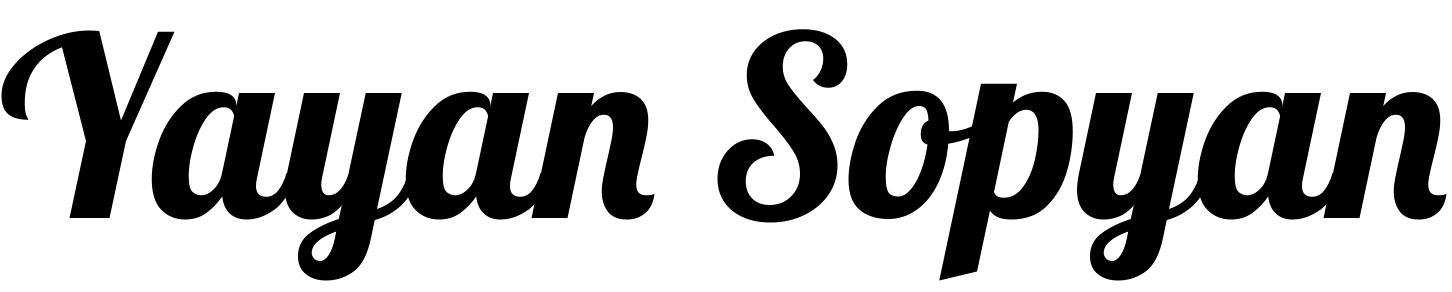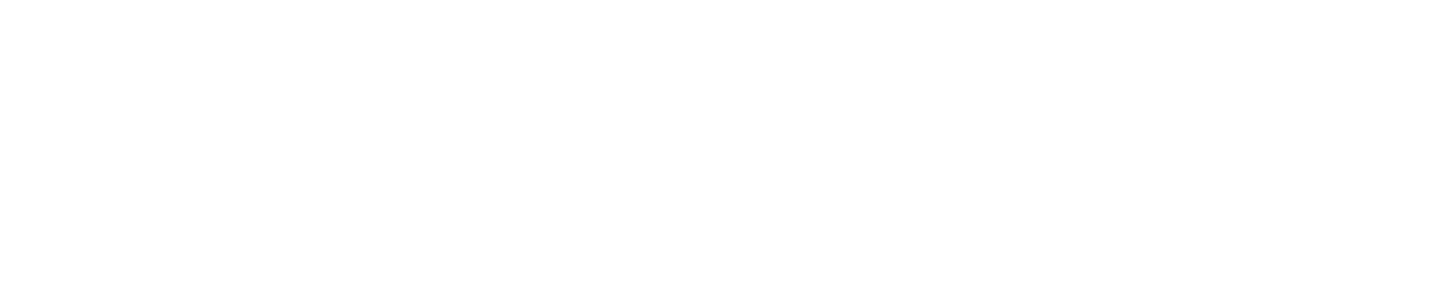Angka bisa menenangkan, tapi juga bisa menenggelamkan manusia di dalamnya. Presiden Republik Indonesia memakai angka dalam urusan program makan bergizi gratis.
“Tiga puluh juta anak dan ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan iya. Ada keracunan makan, iya. Kami hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan, kekurangan, atau kesalahan itu adalah 0,00017 persen," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, seperti dikutip media.
Dengan menekankan angka “0,00017 persen”, kita diajak memandangi persentase itu, seolah-olah nyaris tidak ada masalah dalam program tersebut.
Begini. Statistik sering tampil sebagai bahasa kekuasaan. Angka memberi kesan objektif, netral, bahkan ilmiah. Begitu sebuah pernyataan dilengkapi data, publik cenderung menerimanya tanpa curiga. Padahal, angka tidak pernah sepenuhnya netral. Ia dipilih, dipilah, dan disajikan dalam bingkai tertentu.
Angka yang sama bisa dipakai untuk tujuan berbeda. Persepsi publik pun bisa diarahkan sesuai siapa yang memegang kendali atas narasi statistik itu.
Masalahnya, manusia yang seharusnya dilihat sebagai pribadi dengan tubuh, rasa sakit, dan harapan, berubah jadi sekadar “kasus”. Lalu dari “kasus” menyusut lagi menjadi pecahan persen yang nyaris tak terlihat.
Katakanlah ada seorang anak yang jatuh sakit karena makanan yang dibagikan. Bagi keluarganya, itu tragedi penuh: kepanikan, biaya pengobatan, trauma yang mungkin menetap. Tetapi dalam laporan resmi, anak itu cuma satu titik kecil di antara ribuan titik lain, lalu diperas lagi jadi angka persentase yang hampir nol. Penderitaan pun kehilangan bobot moralnya.
Lihatlah bagaimana angka tidak cuma menciutkan tragedi jadi persentase, tetapi juga bisa dimainkan lewat skala yang dipilih. Dengan angka absolut, ribuan orang sakit tampak serius. Tapi begitu dibagi dengan total penerima jutaan orang, hasilnya persentase yang sangat kecil. Seperti kamera yang bisa zooming mendekat dan menjauh, statistik memberi kendali penuh atas lensa yang dipakai untuk melihat kenyataan.
Yang lebih berbahaya, publik akhirnya terbiasa menganggap korban dalam jumlah tertentu sebagai hal yang normal. Begitu angka disebut kecil, kita menerima begitu saja bahwa ada nyawa yang “wajar” dikorbankan.
Juga, angka rata-rata sering menyembunyikan ketimpangan yang lebih dalam. Ketika statistik tidak menyingkap distribusi, ia menutup mata pada keadilan. Lebih parah lagi, ada orang-orang yang bahkan tidak masuk hitungan sama sekali: tidak terdata, tidak melapor, atau tidak dijangkau. Mereka hilang dua kali—pertama sebagai korban nyata, kedua karena tidak tercatat dalam angka resmi.
Lalu, bagaimana seharusnya statistik diperlakukan ketika menyangkut manusia?
Angka tetap penting. Tanpanya, kita tidak bisa melihat skala persoalan. Tetapi angka tidak boleh diperlakukan sebagai kenyataan penuh. Ia adalah representasi, cermin parsial yang memantulkan sebagian realitas. Etika menuntut kita untuk sadar bahwa di balik tiap angka ada manusia konkret.
Itu berarti perlu, pertama, transparansi, dengan menyajikan data apa adanya berikut keterbatasannya. Kedua, humanisasi, dengan menautkan angka pada kisah nyata yang mengingatkan kita bahwa statistik bukan sekadar digit, melainkan nasib. Ketiga, keadilan, dengan tidak membiarkan rata-rata menenggelamkan kelompok rentan. Keempat, akuntabilitas moral, dengan tetap memikul tanggung jawab penuh atas setiap korban, betapapun kecil persentasenya.
Kita sering terjebak pada dikotomi: memilih angka atau cerita. Padahal kita butuh keduanya sekaligus. Statistik membantu memahami seberapa luas masalah. Cerita manusia mengingatkan seberapa dalam penderitaan tiap individu.
Tanpa angka, kita kehilangan hutan. Tanpa cerita, kita kehilangan pohon. Dan kalau salah satu hilang, kita tersesat membaca realitas.
Statistik tidak boleh menjadi tameng untuk menyingkirkan penderitaan. Ia seharusnya jadi alat memperjuangkan martabat. Di balik “0,00017%” itu ada anak-anak dengan tubuh lemah, orang tua yang panik di rumah sakit, keluarga yang dihantui kecemasan. Mereka bukan sekadar margin of error. Mereka adalah manusia, sama berharganya dengan jutaan penerima lain yang sehat.
Statistik boleh bicara soal skala, tapi empati harus bicara soal martabat. Keduanya tidak boleh saling meniadakan.