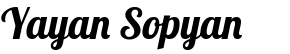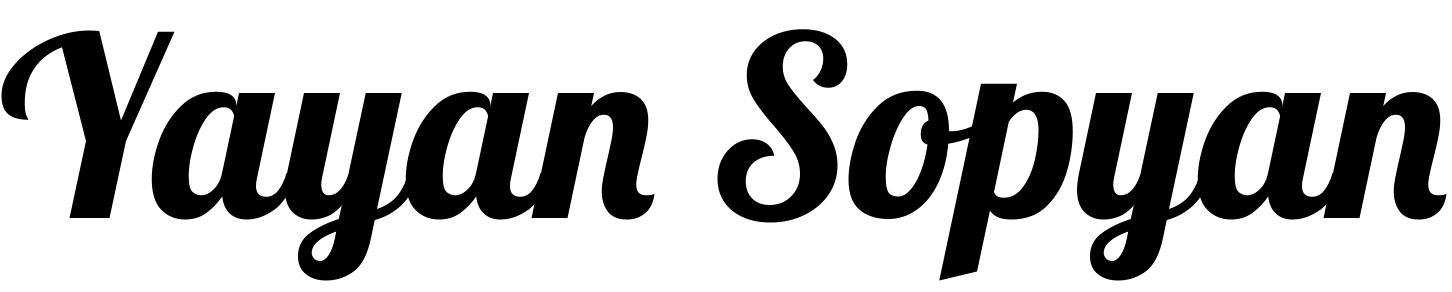“Cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan,” kata Dwi Sasetyaningtyas. Tyas mengucapkannya dengan nada senang dan bahagia setelah menerima surat resmi yang menyatakan anaknya sekarang berkewarganegaraan Britania Raya.
Kalimat Tyas itu tidak mengubah undang-undang, juga tidak menjatuhkan pemerintahan. Tetapi kalimat itu memicu kemarahan banyak orang.
Di sejumlah postingan di media sosial dan komentar-komentar yang menyertainya, kemarahan itu tampak seperti terkait dengan soal fairness. Soal timbal balik. Soal uang pajak rakyat yang dipakai untuk membiayai pendidikan, lalu muncul pernyataan yang terasa menjauh dari identitas kebangsaan.
Apakah kemarahan ini melulu soal fairness?
Kalau sedikit bersabar mencernanya, kita bisa jadi melihat kemarahan banyak orang itu tidak cuma berhenti di sana. Kemarahan itu terasa lebih dalam.
***
Orang-orang di media sosial yang marah itu mungkin berkata ini soal fairness. Memang ada unsur itu. Mereka merasa uang publik harus kembali kepada publik. Bahwa kalau seseorang pernah ditopang oleh dana bersama, ada harapan -secara moral- untuk tetap terhubung dengan komunitas yang membiayainya.
Tetapi fairness di sini tidak berdiri sendiri. Masalah fairness itu bisa jadi lahir dari pengalaman sehari-hari sebagai warga yang merasa sering memberi lebih banyak daripada yang diterima.
Banyak orang merasa sudah cukup lama bersabar. Bersabar melihat kasus korupsi. Bersabar melihat kebijakan yang tidak konsisten. Bersabar dengan janji-janji yang tak selalu ditepati.
Dalam suasana seperti itu, kata “adil” menjadi sensitif. Fairness menjadi kebutuhan emosional yang mendesak.
Karena itu, ketika muncul satu pernyataan yang terdengar seperti menjauh dari Indonesia, reaksi publik tidak berhenti pada hitung-hitungan pajak. Ia menyentuh lapisan yang lebih dalam: rasa cemas tentang arah negeri ini.
Kalau mereka yang punya akses pendidikan tinggi, jaringan global, dan peluang luas pun tampak tidak sepenuhnya yakin untuk menambatkan masa depan anaknya di sini, lalu bagaimana mereka yang tidak punya pilihan serupa?
Kalimat yang diucapkan Tyas itu tidak terdengar sebagai pilihan pribadi saja, melainkan sebagai isyarat bahwa masa depan yang dijanjikan negeri ini belum cukup meyakinkan. Di situlah kekecewaan berubah bentuk, dari soal fairness menjadi pertanyaan yang lebih besar: negara ini sebenarnya sedang berjalan untuk siapa, dan ke mana?
***
Keresahan publik dalam kasus ini mungkin bukan semata kekecewaan kepada satu individu. Itu adalah akumulasi frustrasi yang sudah lama mencari wajah. Itu adalah kemarahan kepada penyelenggara negara yang dianggap gagal menjaga kepercayaan; gagal menghadirkan rasa aman terhadap masa depan.
Tetapi kemarahan kepada negara terlalu besar dan terlalu abstrak. Maka ketika ada peristiwa konkret, kemarahan itu menempel di sana.
Satu kalimat menjadi sasaran. Satu orang menjadi simbol. Padahal yang sedang dipersoalkan jauh lebih luas.
***
Ada paradoks getir di sini.
Rakyat menuntut loyalitas moral dari individu yang pernah dibiayai negara. Pada saat yang sama, rakyat sendiri sedang berjuang mempertahankan kepercayaan mereka pada negara.
Kita ingin orang-orang terbaik tetap percaya pada Indonesia. Tetapi apakah Indonesia, dalam praktik penyelenggaraannya hari ini, cukup memberi alasan untuk percaya?
Itu pertanyaan yang lebih mendasar daripada soal paspor.
***
Barangkali yang membuat kalimat Tyas itu terasa keras bukanlah karena ia anti-Indonesia. Tetapi karena ia terdengar seperti keputusan yang diam-diam diambil oleh banyak orang: kalau ada kesempatan, mungkin lebih aman mencari masa depan di tempat lain.
Ketika keputusan -yang biasanya disimpan itu- diucapkan dengan terang, kita terpaksa menatap kemungkinan yang tidak nyaman: bahwa krisis kepercayaan ini nyata.
Sangat jelas, kemarahan publik bukan sekadar soal fairness. Kemarahan itu adalah alarm bahwa hubungan antara rakyat dan penyelenggara negara sedang retak; bahwa kepercayaan adalah barang yang makin mahal; dan bahwa masa depan tidak bisa terus-menerus dibebankan pada kesetiaan warga, sementara pengelolaan negara berjalan dengan logika kekuasaan sesaat.
Kasus ini mungkin akan berlalu. Timeline akan berganti topik. Tetapi pertanyaan yang ditinggalkannya lebih sulit dihapus:
Kalau rakyat sendiri mulai ragu pada arah negaranya, siapa yang sebenarnya harus lebih dulu memperbaiki diri? Warganya, atau penyelenggaranya?
Dan mungkin di situlah inti kemarahan yang kita saksikan hari ini.
Ya, bisa jadi, kemarahan kita sebenarnya bukan untuk Tyas.