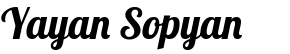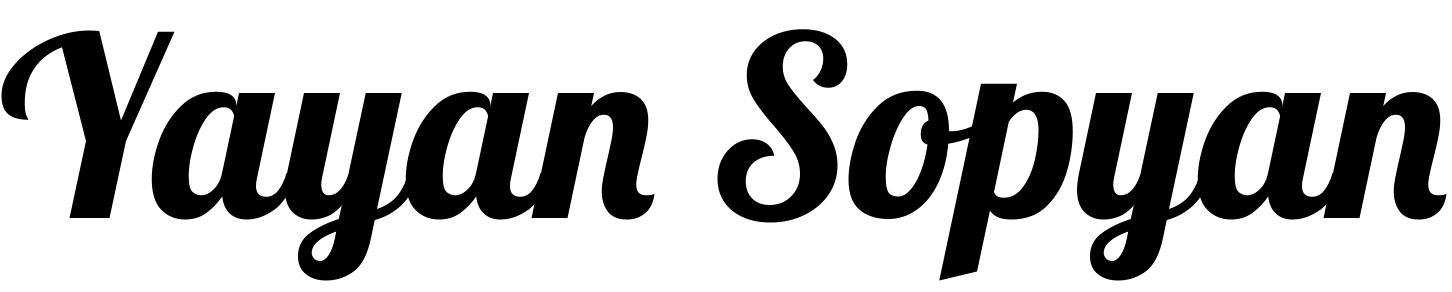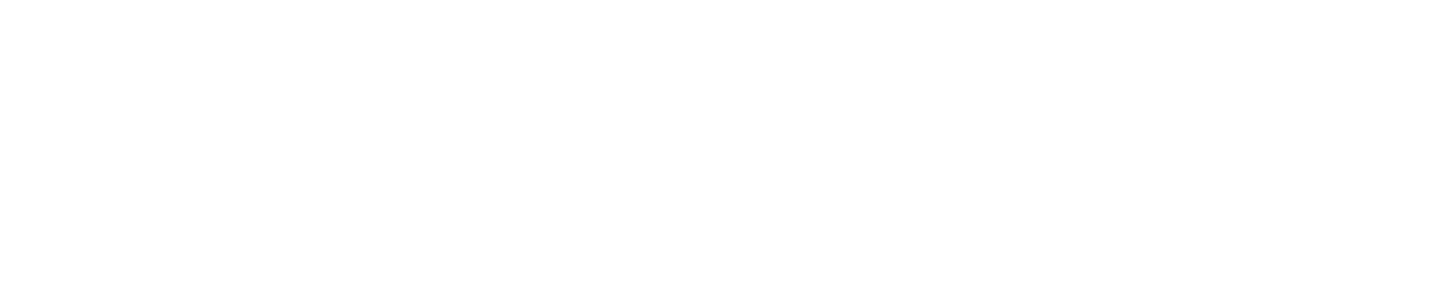Kata esai terdengar seperti satu bentuk tulisan, dengan satu rumus menulis yang sama untuk keperluan apa saja. Itu anggapan keliru. Esai memang satu nama, tapi jalan dan caranya bisa sangat berbeda.
Menulis esai untuk keperluan aplikasi beasiswa jelas berbeda dengan menulis esai personal di blog pribadi; akan berbeda juga dengan menulis esai opini di media; akan berbeda lagi dengan menulis esai untuk urusan akademis. Coba kita intip beberapa perbedaannya.
Esai beasiswa itu suara dalam diri kita. Isinya bukan untuk memamerkan prestasi. Menulis esai beasiswa adalah kesempatan untuk memperkenalkan dirimu secara jujur dan terarah. Kamu menulis kepada seseorang yang ingin tahu: apakah kamu punya niat kuat, komitmen jangka panjang, dan cerita hidup yang bisa dipercaya?
Kuncinya, esai beasiswa itu reflektif, personal, tetapi tetap fokus pada kontribusi dan visi ke depan.
Bagaimana dengan esai personal di blog pribadi?
Begini. Blog adalah tempat paling lentur untuk menulis esai personal. Kamu bisa jujur, bisa bercerita, bahkan bisa bercanda. Tapi jangan salah, esai blog yang baik tetap punya arah, tetap menyampaikan sesuatu yang bermakna. Bedanya, kamu mengajak pembaca duduk bersama, bukan berdiri di podium. Gaya menulisnya bisa seperti ngobrol dengan teman. Biar pun begitu, idenya tetap harus punya tujuan: menggerakkan, menyentuh, atau menyadarkan.
Menulis esai di blog pribadi itu seperti menulis di kamar sendiri yang terbuka bagi siapapun yang ingin membaca tulisan-tulisanmu. Bahkan kamu bisa mengundang orang lain untuk datang ke kamar itu. Jelas, itu berbeda dengan menulis esai opini di media pers: kamu seperti masuk ke ruang baca publik untuk menyampaikan pendapatmu tentang sebuah isu ke khalayak.
Esai opini di media pers itu bukan soal siapa kamu, tapi apa yang kamu pikirkan. Esai media harus ringkas, tajam, berbasis argumen dan data. Kadang kamu harus menulis dalam 700 kata, tetapi dengan bobot yang bisa mengubah pandangan orang. Di sini, kamu perlu keberanian menyatakan posisi, sekaligus kehati-hatian agar tidak terjebak klaim kosong.
Beda lagi dengan esai akademis. Dalam esai akademis, kamu tidak sedang menyampaikan opini pribadi, melainkan mengembangkan argumen berdasarkan teori, riset, dan metodologi. Di sini kamu akan diuji apakah bisa berpikir jernih, logis, dan sistematis.
Struktur esai akademis memang kaku, tetapi bukan tanpa alasan. Karena yang dinilai bukan hanya ide kamu, tapi proses berpikir dan dasar analitisnya.
Sekarang kita balik pertanyaannya: meskipun berbeda-beda, apakah ada persamaan di antara jenis-jenis esai itu?
Ada. Apa pun jenis esainya, ada lima hal mendasar yang selalu menjadi penopang tulisan yang baik.
- Semua esai dibangun atas satu ide utama. Tanpa ide utama yang jelas, pembaca akan hilang arah.
- Semua esai punya struktur tiga bagian: pembuka, isi, penutup. Format boleh bebas, tapi struktur ini adalah tulang punggungnya.
- Semua esai berusaha membuat pembaca memahami sesuatu. Mau menginspirasi, menjelaskan, meyakinkan, atau menantang -intinya tetap sama: membuat pembaca melihat sesuatu dari sudut pandangmu.
- Semua esai butuh kejernihan berpikir. Kalimat boleh panjang atau pendek, tapi harus mengalir dan mudah dipahami.
- Semua esai memuat suara penulis. Dalam bentuk apa pun, esai selalu membawa jejak pemikiran dan perasaanmu.
Jadi, setelah melihat perbedaan dan persamaan itu, apa implikasinya dalam proses menulis esai? Ya, mulailah dengan menentukan tiga hal ini:
- Siapa yang akan membaca esaimu?
- Apa yang kamu ingin mereka rasakan atau pikirkan setelah membaca?
- Apa posisi dan keunikanmu sebagai penulis?
Dari situ, kamu bisa menentukan gaya, struktur, dan arah esai yang kamu tulis.
Menulis esai itu bukan sekadar memenuhi tugas atau syarat administrasi. Ini tentang melatih cara berpikir dan menyampaikan diri secara utuh. Tidak ada rumus tunggal, tapi selalu ada prinsip yang bisa jadi pegangan.
Jadi, apa pun jenis esainya, mulai saja dari satu hal: tahu apa yang ingin kamu sampaikan—dan kenapa itu penting untuk orang lain.