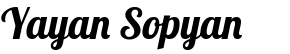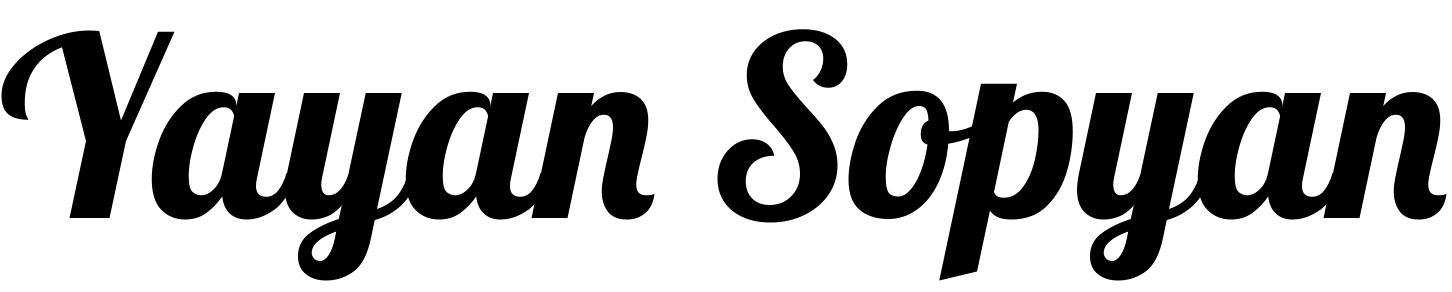Itu mungkin tahun 79 atau 80. Saya lupa persisnya.
Selain menjadi tukang jahit, Bapak membuka toko kelontong. Khusus bulan Ramadhan, jenis barang dagangan bertambah di toko kami: pakaian, sandal, dan sepatu. Kalau kopiah dan sajadah memang tersedia juga di luar Ramadhan.
Pada hari terakhir Ramadhan biasanya semua toko di sekitar pasar -termasuk toko kecil kami- sudah ramai sekali. Kalau sudah ramai begitu, seluruh anggota keluarga dikerahkan untuk melayani pembeli.
Saya masih ingat betapa penuh sesaknya toko kecil kami pada malam itu. Para pembeli berebut memilih sandal, sepatu, atau pakaian yang kami taruh di dus besar. Mereka bisa memilih sendiri barang yang mereka mau beli.
Bukan cuma memilih, dalam suasana Malam Takbiran, lumrah pada masa itu orang menjajal barang yang mereka mau beli. Bukan pemandangan yang aneh jika calon pembeli membuka kemasan sepatu atau sandal, lalu mereka mencobanya. Jika merasa cocok, mereka akan minta pilihannya segera dibungkus, lalu membayar sesuai harga. Jika tidak cocok, barang dikembalikan ke dus besar seadanya.
Beruntung kalau barang-barang itu tetap ada di dus besar lalu dipilih oleh calon pembeli lainnya. Tidak sedikit yang jatuh ke lantai dan tidak berhasil dikembalikan, lalu tanpa sengaja tersepak oleh kerumunan, terlempar ke kolong salah satu rak di toko kami, dan tersembunyi di sana untuk waktu yang lama sekali.
Tidak seperti orang lain yang berusaha masuk ke toko untuk berbelanja, seorang ibu dengan satu anak dalam gendongannya dan satu anak lelaki dalam tuntunannya hanya hilir mudik dari depan toko kami ke depan toko sebelah. Berkali-kali saya melihat mereka lalulalang di luar saja sambil mengamati keramaian di dalam toko.
Percaya atau tidak, sebelum jam 8 malam, stok pakaian, sepatu, sandal nyaris ludes. Sisanya sangat sedikit dan berserakan. Banyak barang keluar dari bungkusnya. Beberapa sepatu dan sandal terlepas dari pasangannya.
Hampir pukul 20:30 malam itu, toko kami mulai sepi. Bukan karena tidak ada lagi orang yang mau berbelanja, melainkan karena tak ada lagi stok barang yang bisa kami jual. Bapak memerintahkan anak-anaknya untuk membantu menutup toko.
Seorang lelaki tergopoh-gopoh masuk bersama si ibu yang menggendong anak kecil dan menuntun bocah lelaki tadi.
Wajah si ayah -si lelaki itu- tampak capek sekali.
"Sana pilih baju sama sepatunya," kata si ayah agak berbisik.
Si ibu -perempuan itu- menyapukan pandangannya ke sekeliling toko kami. Tak ada barang yang bisa dipilih. Tinggal sisa-sisa.
Si anak -bocah lelaki itu- bergegas ke rak tempat tumpukan sandal dan sepatu yang mungkin sejak sore sudah dia incar. Dia melongokkan kepalanya ke serakan sepatu. Dia mengambil satu dua sepatu lalu ditaruh lagi. Dia lakukan itu berulang-ulang.
"Sepatu dan sandalnya sudah habis," kata Bapak.
Tapi si bocah dan ayahnya tidak menggubris. Mereka tetap mencari-cari sepatu.
"Yang ini saja," bisik si ayah.
"Tapi kebesaran," timpal si anak.
"Tidak apa-apa," bujuk si ayah.
"Tapi ini kiri semua," kata si anak.
"Tidak apa-apa," kata si ayah.
Bapak menghampiri mereka.
"Maaf, ini tidak bisa saya jual," kata Bapak.
Wajah si anak berubah memelas. Begitu juga wajah ayahnya.
"Toko lain sudah tutup, Pak Haji," kata si ayah seolah meminta diijinkan membeli sepatu kiri semua yang kebesaran buat anaknya.
"Saya tidak menjual sepatu kiri semua ini. Maaf," Bapak tetap menolak.
Si ibu -perempuan yang menggendong bayi itu- diam saja, tidak terlibat dalam percakapan. Sorot matanya tidak menyatakan dirinya hadir di toko kami. Entah sedang berada dimana pikiran perempuan itu.
Dia mungkin sudah menunggu suaminya sejak siang tadi. Suaminya baru tiba pada malam hari ketika hampir semua toko sudah tutup dan kehabisan barang dagangan.
Terkecuali anak yang digendong, saya masih ingat bagaimana sorot mata mereka bertiga ketika meninggalkan toko kami. Dan itu hampir selalu muncul dalam ingatan saya di setiap Malam Takbiran.