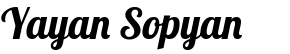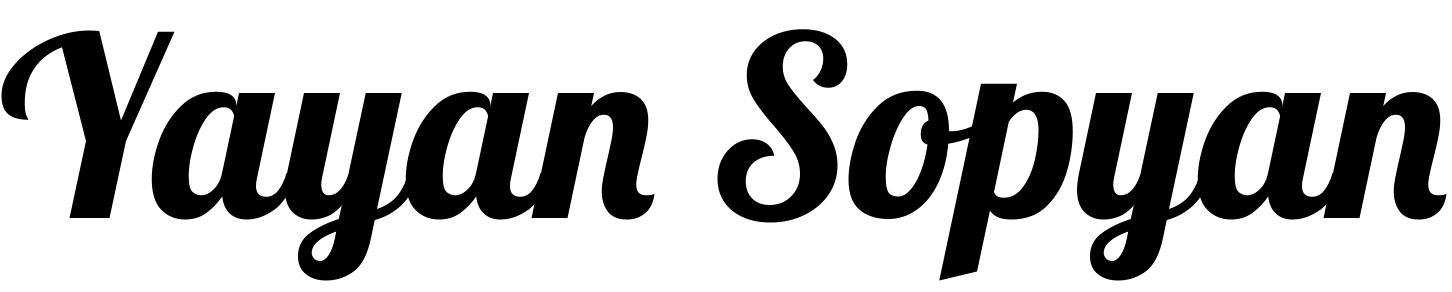Menulislah agar tidak bernasib seperti Socrates. Meskipun ia begitu berpengaruh dalam filsafat, hampir tidak ada catatan tertulis yang ditinggalkan Socrates.
Semua yang kita ketahui tentang Socrates datang dari karya-karya orang lain, terutama Plato, Xenophon, dan Aristophanes. Kita bahkan sebetulnya tidak tahu persis sosok sang filsuf itu karena ketiga orang itu menghadirkan wajah Socrates yang berbeda-beda.
Tiga potret Socrates
Plato menggambarkan Socrates sebagai sosok cerdas, mendalam, dan teguh dalam pendirian. Lihatlah bagaimana Plato menggambarkan pembelaan diri Socrates saat diadili di Athena pada tahun 399 SM atas tuduhan merusak pemuda Athena dan tidak mempercayai dewa-dewa yang diakui oleh negara.
“Wahai orang-orang Athena, aku menghormati dan mencintai kalian; tetapi aku akan tetap menaati tuhan daripada kalian, dan selama aku masih hidup dan punya kekuatan, aku tidak akan berhenti berfilsafat dan menasihati kalian serta memberi peringatan kepada siapa saja yang kutemui … apa pun yang kalian lakukan, pahamilah bahwa aku tidak akan pernah menyerah melakukan ini, meskipun aku harus mati berkali-kali,” kata Socrates dalam catatan Plato itu. Di mata Plato, Socrates adalah simbol keberanian intelektual yang menginspirasi generasi berikutnya untuk selalu mempertanyakan dan mencari kebenaran.
Di mata Xenophon, sosok Socrates tidak seperti itu. Xenophon menyajikan gambaran Socrates yang lebih sederhana. Dalam The Memorabilia karya Xenophon, Socrates terlihat sebagai seorang moralis praktis, bukan intelektual besar seperti yang dipersepsikan Plato. Ia lebih dekat dengan orang biasa, menawarkan pandangan hidup sehari-hari yang relevan.
Di salah satu bagian dari The Memorabilia, Xenophon menceritakan dialog Socrates dengan Aristippus. Dalam percakapan itu Socrates menekankan bahwa kehidupan yang baik adalah tentang melatih diri untuk menghindari keinginan yang berlebihan dan hidup dengan kebajikan. Socrates dihadirkan sebagai seorang filsuf yang tidak jauh dari kehidupan keseharian warga Athena.
Ada pandangan lain yang lebih kontras dari Aristophanes. Dalam komedi The Clouds karya Aristophanes, Socrates diparodikan sebagai seseorang yang konyol dan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ia digambarkan sebagai seorang yang memusingkan dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban, seakan-akan terlalu pintar untuk kebaikan dirinya sendiri. Potret ini, meskipun bersifat satir, memperlihatkan sisi lain dari bagaimana masyarakat melihat peran Socrates di tengah mereka.
Bukan soal pendokumentasian saja
Andai saja Socrates meninggalkan tulisan, bisa jadi kita akan mengenal satu wajah yang lebih utuh, langsung dari pemikirannya sendiri.
Ajakan saya untuk menulis itu bukan sekadar melulu terkait dengan pendokumentasian peristiwa-peristiwa dan pemikiran-pemikiran kita sendiri. Ajakan ini lebih berurusan dengan cara untuk mengolah dan melengkapi proses berpikir.
Dialog lisan, seperti yang sering dipraktikkan oleh Socrates, adalah alat yang bagus untuk mempertajam ide melalui pertukaran gagasan secara langsung. Namun, tulisan memiliki kekuatan yang berbeda. Saat menulis, kita diberi ruang untuk merenung, menyusun ulang pemikiran, dan memperbaiki argumen.
Menulis memaksa kita untuk berpikir lebih runtut dan mendalam, memastikan setiap ide dikaji secara tuntas sebelum diabadikan dalam bentuk teks. Menulis tak hanya mencatat apa yang kita pikirkan, tetapi juga memberi struktur dan kedalaman pada pikiran tersebut.
Dalam dialog lisan, ide-ide sering kali muncul secara spontan—terkadang dalam bentuk yang masih mentah. Seorang pembicara mungkin merasa bahwa gagasannya telah jelas, tetapi pendengar dapat menangkapnya dengan cara yang berbeda, atau bahkan keliru.
Berbeda dengan itu, menulis memberikan kesempatan untuk menguji ulang pikiran-pikiran kita sendiri. Ketika kita menuangkan sebuah ide ke dalam kata-kata tertulis, tidak jarang kita menemukan celah, kekaburan, atau kontradiksi yang tak terlihat dalam percakapan biasa. Dengan tulisan, kita bisa mengoreksi, memperjelas, dan menyempurnakan apa yang ingin kita sampaikan.
Kita mungkin tak bisa mengubah sejarah dan melihat Socrates menulis sendiri ajarannya. Namun cerita Socrates itu mengingatkan bahwa menulis adalah sarana penting untuk melengkapi dialog. Dengan menulis, kita tak hanya menyampaikan, tetapi juga merenungkan dan menjaga pemikiran dan pengalaman kita, memastikan bahwa ia bertahan lebih lama, dipahami lebih utuh, dan tidak mudah terdistorsi oleh interpretasi orang lain.
Jadi, sebelum ide-ide besar hilang dalam percakapan atau terlupakan di antara pikiran yang tak terucapkan, menulislah. Menulis bukan hanya soal berbagi dengan orang lain, tetapi juga tentang berdialog dengan diri sendiri—menggali lebih dalam, mengkritisi, dan membentuk ulang pemikiran kita.