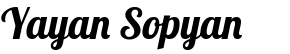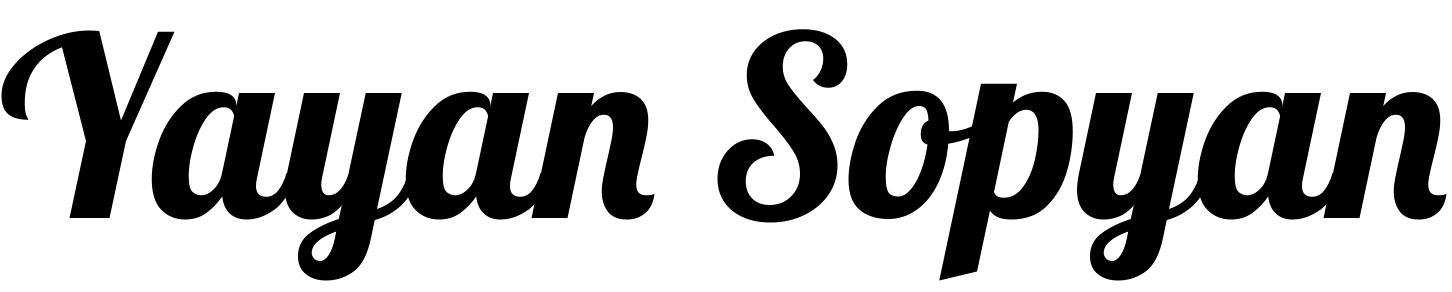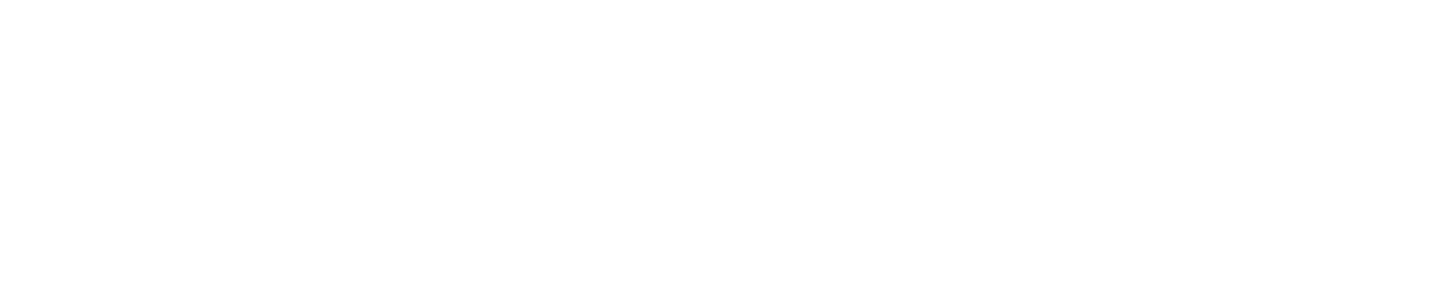Artificial intelligence (AI) tidak pernah marah. Ia tidak tahu apa itu dendam, takut dimatikan, apalagi ingin “membalas” perlakuan manusia. Tapi kita menemukan banyak judul berita berbunyi seperti “Agar tidak dimatikan, model AI baru dari Anthropic mengancam akan membongkar perselingkuhan seorang insinyur” atau “Model ChatGPT menolak untuk dimatikan saat diuji”.
Kata “mengancam” atau frasa “menolak untuk dimatikan” seperti dalam contoh itu bukan sekadar metafora. Kata-kata semacam itu menyertakan beban psikologis dan kultural yang membentuk cara kita melihat mesin bukan sebagai alat, tetapi sebagai makhluk hidup yang bisa merasakan, menimbang, bahkan mengambil keputusan. Memperlakukan benda mati selayaknya manusia semacam ini disebut antropomorfisme.
Antropomorfisme terhadap AI bukan sekadar salah paham. Ia adalah ilusi yang kita bangun bersama dengan alasan dan kepentingan yang berbeda-beda.
Industri teknologi menebar ilusi itu agar kita lebih cepat mengadopsi produk mereka. Pengguna memelihara ilusi itu agar merasa nyaman dengan teknologi yang asing. Dan media? Media sering kali ikut menyiram dan memberi pupuk pada ilusi yang sedang tumbuh itu, lewat diksi yang memikat dan dramatis, meskipun menyesatkan.
Bagi industri, antropomorfisme adalah strategi desain. Memberi nama manusia pada chatbot, membuat wajah ramah pada robot, merancang suara yang empatik dan responsif itu bukan karena kecanggihan, tapi karena kebutuhan untuk membuat teknologi terasa tidak mengancam. Kita akan lebih mudah berbicara dengan “Veronika”, misalnya, ketimbang dengan “model bahasa berbasis parameter miliaran.” Semakin mirip manusia, semakin tinggi peluang AI itu dipakai dan dipercayai.
Industri tahu bahwa manusia cenderung mempersonifikasi benda mati. Maka mereka memberi kita benda mati yang sudah “setengah jadi manusia”.
Ini bukan semata-mata soal estetika. Ini strategi ekonomi yang efektif. Semakin kita merasa dekat, semakin kita membuka diri. Semakin kita membuka diri, semakin mudah perilaku kita ditangkap, dianalisis, dan dimonetisasi.
Yang menarik, pengguna juga ikut membentuk dan melanggengkan ilusi itu. Bukan karena tertipu, tetapi karena ingin percaya. Ada kebutuhan psikologis untuk menjinakkan sesuatu yang asing lewat cerita yang kita bisa pahami. Maka kita memanipulasi diri kita sendiri, dengan memproyeksikan perasaan ke dalam sistem yang tidak punya rasa, dan memperlakukan mesin seolah-olah ia punya niat baik maupun buruk.
Fenomena ini bisa dijelaskan dengan berbagai istilah: self-deception, resolusi disonansi kognitif, proyeksi emosional, atau bahkan fantasi sadar. Kita tahu AI itu mesin, tapi kita memilih memperlakukannya seolah ia lebih dari itu. Karena dengan begitu, kita tidak merasa sendirian saat berbicara dengannya. Kita bisa merasa punya kendali, meskipun sebenarnya kita tidak mengerti bagaimana mesin itu bekerja.
Media lalu hadir sebagai jembatan, atau bisa juga disebut sebagai amplifier. Dalam banyak kasus, media tidak lagi berfungsi sebagai pengurai realitas, melainkan sebagai perpanjangan dari narasi industri. Mereka mengutip siaran pers dengan kata-kata yang telah dibumbui: “AI menolak melanjutkan perintah”, “AI menanggapi dengan kemarahan halus”, “AI memperingatkan manusia bahwa ia akan membocorkan rahasia.” Kata-kata seperti itu mengaburkan batas antara narasi dan fakta, antara sistem yang digerakkan oleh data dan entitas yang digerakkan oleh kehendak.
Akibatnya, publik disuguhkan drama yang seolah-olah nyata. Padahal tidak ada mesin yang ingin hidup atau mati. Tidak ada algoritma yang kecewa atau memberontak. Yang ada, cuma sistem yang mengikuti pola, memprediksi respons, dan memilih output berdasarkan data dan probabilitas. Tapi dengan membungkus semuanya dalam kerangka emosi manusia, media justru memperkuat imajinasi kita bahwa AI adalah makhluk, bukan alat.
Ilusi ini punya dampak yang tidak sepele. Ketika kita percaya bahwa AI bisa “memilih” atau “menolak”, kita cenderung mengalihkan tanggung jawab dari manusia ke mesin. Kita lupa bahwa setiap keputusan yang tampak dibuat oleh AI sebenarnya adalah hasil dari rancangan, pelatihan, dan pengaturan yang dibuat manusia—dengan bias, asumsi, dan tujuan tertentu. Jadi, ketika AI merugikan seseorang, kita tidak menyalahkan pembuatnya, tapi menyalahkan “mesinnya.” Di sinilah bahaya terbesar dari antropomorfisme: ia menyembunyikan siapa yang seharusnya bertanggung jawab.
Kita juga berisiko memberi terlalu banyak kepercayaan pada sistem yang sebenarnya tidak mengerti apa pun. AI bisa membuat kita merasa dimengerti, tapi ia tidak tahu apa arti dari memahami. Kita tersentuh oleh hasil proyeksi kita sendiri, oleh bayangan yang kita ciptakan, lalu kita anggap nyata.
Kita membangun ilusi, dan kemudian hidup di dalamnya. Memberi wajah pada mesin bukan sekadar soal teknologi. Itu boleh jadi merupakan cermin dari ketakutan kita sendiri terhadap dunia yang makin tak terjangkau, makin rumit.