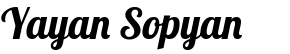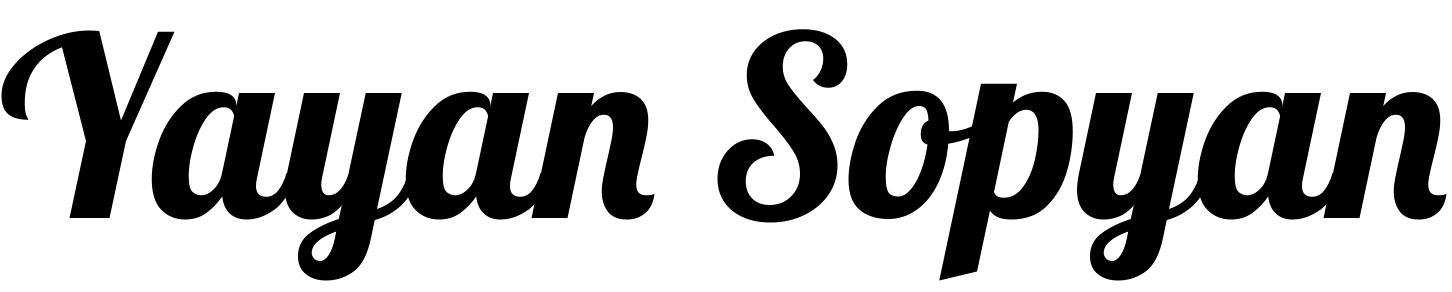Berita mengenai terpilihnya Roh Moo-hyun sebagai presiden Korea Selatan yang oleh jurnalis ditulis sebagai "Jadi Presiden Karena Internet" memicu sejumlah perbincang di mailing list GENETIK@, yang di dalamnya saya turut menjadi salah seorang susbcriber. Subyek ini kemudian meluas menjadi beragam subyek.Beberapa diantaranya bersubyek
Sampai kemudian Heru Nugroho menurunkan subyek baru
Di banyak negara, gaptek sudah dianggap sikap primitif......Tulisan ini memancing perhatian saya. Saya pun akhirnya terlibat dalam diskusi ini, yang juga kemudian berkembang menjadi subyek-subyek yang lain. Berikut ini adalah beberapa posting saya dalam diskusi tersebut.Di Indonesia, mungkin gak perlu "menerawang" jauh dulu........
pada tahap awal, berani gak kita secara nasional menetapkan satu etika nasional: gaptek (gagap teknologi) adalah sebuah sikap primitif !?Semoga bermanfaat
"jadi presiden gara-gara egovt" lewat posting Bambang SN, bersubyek "dunia tanpa kertas...." lewat posting Mas Wigrantoro, bersubyek "less paper vs paper less", dan (mungkin) sejumlah subyek lain. Ini tampaknya berlangsung bahkan di lintas mailing list: Telematika dan mastel-anggota. "gaptek adalah sikap primitif". Heru menulis,
 Heru,
Heru,
kayaknya untuk kultur kita saat ini, ajakan Heru untuk "menetapkan satu etika nasional:gaptek (gagap teknologi) adalah sebuah sikap primitif" adalah sikap yang paling primitif.
Dalam kultur kita saat ini rasanya gaptek lebih pantas diposisikan sebagai akibat ketimbang sebagai sebab.
Menurut saya, kegaptekan masyarakat kita adalah telur yang dihasilkan oleh gapkom (gagap komunikasi) dan gapdik (gagap didik) dari minoritas meltek (melek teknologi) dalam masyarakat kita, dan hasil dari butubivisbud (buta tuli bisu visi kebudayaan) mereka yang disebut/meyebut dirinya sebagai pemimpin bangsa saat ini.
Salam
Saya kira, apa yang dipaparkan Heru memang refleksikan beberapa bagian besar fenomena kultur kita yang berkait dengan apresiasi terhadap peradaban teknologi (tentu, tidak harus TI). Apa yang dilihat Heru, tidak jauh berbeda dengan apa yang saya lihat.
Tentu, selain dari saya, Heru Nugroho mendapat tanggapan dari sejumlah peserta mailing list. Tampaknya Heru merasa bertanggungjawab untuk memperjelas beberapa bagian hal dalam tulisan sebelumnya. Ia pun melayangkan penjelasannya di bawah subyek "kriteria gaptek itu apa ??" pada 1/3/2003.Atas penjelasannya ini, saya kembali melayangkan tanggapan sebagai berikut:
Apresiasi kebanyakan dari kita terhadap teknologi -menurut saya- masih kurang bersentuhan dengan asas manfaat, asas pragmatis dan asas tepat guna. Sampai saat ini, saya masih menangkap kesan bahwa apresiasi kebanyakan dari kita terhadap teknologi lebih bersifat snobistis.
Snobisme mendorong orang yang punya (the have) untuk MEMILIKI barang-barang teknologi dalam rangka mempertontonkan status diri dalam sebuah tatanan sosial eknomi dan budaya, sebagai suatu kelangenan. Pada saat yang sama snobisme membangun ilusi orang yang tak punya (the have not) untuk menjaga jarak terhadap barang-barang teknologi karena tak tersentuh (untouchable) dan terlalu terhormat.
Dalam kacamata snobisme, MEMILIKI dan MENGGUNAKAN menjadi hal yang melampaui pentingnya MEMANFAATKAN dan MENDAYAGUNAKAN secara tepat guna. Dengan memakai kacamata snobisme, persoalan nyata kesenjangan digital (digital divide) akan tampak seperti sebuah ilusi dan sesuatu yang artifisial. Snobisme dalam mengapresiasi teknologi mampu menutup penglihatan kita terhadap cakrawala peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan penting yang tersaji dalam peradaban teknologi. Tentu, peluang dan kesempatan tersebut tidak selalu berarti dalam konteks kebaikan.
Jika gaptek dipahami dalam konteks ini maka saya dan Heru mungkin dalam 'frekuensi' yang sama.
Tapi -menurut saya- apresiasi terhadap teknologi semacam itu bukanlah 'gawan bayen', bukan bawaan lahir, bukan kodrat. Apresiasi dalam tataran apapun merupakan hasil bentukan interaksi kultural diantara anggota masyarakatnya. Dan kalau mau jujur, apresiasi kebanyakan kita terhadap teknologi tersebut secara dominan dibentuk oleh citra teknologi yang dimunculkan oleh kelompok minoritas dari kalangan melek teknologi. Minoritas melek teknologi inilah yang sekarang menjadi kelompok priyai baru dalam masyarakat gaptek kita.
Oleh karena itu, jika apresiasi kebanyakan dari kita terhadap teknologi itu tidak tepat, maka yang cukup harus bertanggungjawab atas ketidaktepatan itu adalah para priyai-priyai melek teknologi ini. Jika ada seseorang yang memandang "teknologi itu rumit", tolong jangan salahkan orang itu. Sebaiknya, tuding saja para priyai-priyai melek teknologi sebagai penyebab dari munculnya citra rumit pada teknologi.
Gaptek bisa mengakibatkan sesuatu. Tapi gaptek juga disebabkan oleh sesuatu. Selama ini, saya rasa, para priyayi melek teknologi terlalu tertarik untuk membahas "Gaptek bisa mengakibatkan sesuatu" (gaptek sebagai sebab). Saya mendapatkan kesan bahwa para priyai ini kurang cukup bercermin diri untuk menghadapi posisi gaptek sebagai akibat.
Para priyai ini (yang bisa saja terdiri dari para jurnalis, pedagang, teknisi, dan praktisi teknologi) tampaknya sering lupa bahwa mereka sendiri punya problem kegagapan:
- Gagap komunikasi. Ternyata tidak gampang menemukan orang yang melek teknologi yang mampu mengkomunikasikan kenyataan-kenyataan teknologi secara jernih dan mudah dipahami oleh beragam kalangan.
- Gagap didik. Ternyata tidak banyak orang yang melek teknologi yang mampu mendidik banyak kalangan dengan suatu peta kebudayaan yang jelas, komprehensif dan nyata.
Itulah sebabnya saya menganggap ajakan Heru untuk "menetapkan satu etika nasional:gaptek (gagap teknologi) adalah sebuah sikap primitif" dalam kultur masyarakat kita saat ini merupakan sikap yang paling primitif, yang paling purba. Bagi saya (dan kalau saya tidak salah membaca tulisannya, mungkin bagi Heru juga), primitif bukanlah sebuah ukuran nilai, melainkan hanya nama bagi sebuah fase dalam evolusi (kebudayaan dan peradaban).
Ajakan perintah etis ala Heru ini mengingatkan kita pada perintah etis yang dilontarkan oleh kelompok elit dalam masyarakat purba; yakni perintah etis yang menjadi elitis karena tidak didukung oleh infrastruktur dan suprastruktur kultural yang memungkinkan untuk dapat dicapai dan dipenuhi secara lebih luas oleh kelompok masyarakat lain.
Salam
Ya, saya kira, memang di sini perbedaan mendasar kita. Dan saya sudah dapat membacanya sejak posting awal ajakan Heru untuk menetapkan "etika nasional" tersebut. Itulah sebabnya saya (tetap) memandang ajakan Heru sebagai sebuah sikap yang paling primitif.
Heru merespon tanggapan saya di atas lewat posting bersubyek "Visi....." pada 2/3/2003. Adi Prasaja merespon posting ini beberapa jam kemudian.Sedangkan saya meresponnya sehari kemudian. Berikut tanggapan saya tersebut:
Keyakinan bahwa pemimpin itu dilahirkan adalah serupa dengan keyakinan para dukun dalam masyarakat purba ketika mereka mencari bayi yang ditakdirkan akan menggantikannya atau menggantikan posisi kepala sukunya. Sebuah keyakinan yang menampikkan peran interaksi dan dinamika manusia dalam membangun kebudayaan dan peradabannya. Sebuah keyakinan yang menepis peran campur tangan masyarakat manusia dalam menentukan sejarahnya sendiri. Sebuah keyakinan yang elitis, feodalistis, dan fatalistis.
Saya percaya pada kehadiran talenta, namun rasanya tak bisa dimengerti jika masyarakat manusia menyerahkan hidupnya pada talenta. Saya setuju dengan pendapat Adi bahwa "kalau dibilang melulu genotif (dilahirkan, bawaan lahir), pasti salah". Sangatlah tidak masuk akal bagi kita untuk nongkrongi sekian persalinan demi menemukan dan menentukan bayi yang kelak menjadi pemimpin kita di masa depan, yang kelak menjadi orang yang melek teknologi. Sekurangnya, saya tak punya waktu untuk menunggui setiap ibu yang akan melahirkan bayinya.
Sebetulnya, menurut saya, cukup ironis (meski tentu boleh-boleh saja) bahwa ada pandangan yang fatalistis hadir dalam sebuah milis gerakan seperti GENETIKA ini. Sebuah gerakan -apapun itu- mengasumsikan kepercayaan kepada perubahan yang dihasilkan oleh peran campur tangan manusia, bukan oleh semata-mata garis nasib bawaan lahir.
Point saya sangat sederhana: Minoritas melek teknologi tidak pantas lepas tangan dan berputus asa atas kegaptekan mayoritas masyarakat di sekelilingnya. Dan sangat tidak patut bagi minoritas melek teknologi untuk bahkan menikmati kegaptekan masyarakat sekelilingnya dengan memposisikan diri sebagai priyai-priyai baru di atasnya. Dan salah satu tindakan yang diperlukan untuk itu adalah mengevaluasi visi dan tindakan kelompok minoritas melek teknologi itu sendiri.
Tentu, tentu, pada gilirannya boleh jadi kelompok minoritas melek teknologi ini menemukan situasi-batas yang memberikan alasan kepada mereka untuk berkata pada dirinya sendiri, "Kami sudah melakukannya". Bagaimanapun kita sudah terlanjur kenal tiga variabel penting yang mendorong orang pada sebuah tindakan: tahu, mampu, dan mau. Namun rasanya situasi-batas itu sampai saat ini belum mereka hadapi.
Saya setuju, terlalu banyak orang yang dianggap pemimpin atau kebetulan dalam posisi memimpin saat ini tidaklah cukup punya visi yang mengarah pada pembangunan masyarakat yang melek teknologi. Dan, seperti saya tulis pada posting pertama, gapteknya masyarakat kita juga dihasilkan oleh para pemimpin palsu yang buta tuli bisu terhadap visi kebudayaan. Tapi kedunguan para pemimpin palsu ini sepatutnya bukan menjadi situasi batas bagi upaya me-melek-teknologi-kan lebih banyak orang.
Hanya sebuah sikap sederhana yang kita butuhkan untuk menghadapi para pemimpin palsu yang dungu: "Lupakan dan tinggalkan mereka". Dalam level dan skala tertentu, komunitas milis ini sudah memperlihatkan independensi dan resistensi terhadap rejim budaya yang dungu, lewat gerakan VOIP Merdeka.
Jadi, sayang rasanya jika kita harus menghabiskan energi untuk meratapi kedunguan para pemimpin palsu.
Salam
Teman-teman,
Tulisan saya tersebut ditanggapi kembali oleh Heru dan Roy Tomirei.Topik pembicaraan, menurut saya (dan mungkin juga menurut sebagian anggota milis lainnya), terasa berkembang ke mana-mana dan tak terlalu fokus. Dan Heru sendiri terkesan ingin menyudahinya.
Saya juga agak enggan berdiskusi yang terlalu melebar. Berikut respon saya atas posting Roy dan Heru (kutipan tulisan Roy dan Heru disajikan dalam huruf italic):
Roy:
seruan antiprimitivisme bung heru menurut yang saya tangkap tidak dimaksudkan untuk memberi privillege kepada kaum yang tercerahkan di bidang teknologi -- yang anda sebut sbg priyayi teknologi -- dan mengkotakkan golongan lainnya, melainkan untuk mendorong orang bergerak maju. garis batas atau tolok ukurnya adalah kegaptekan itu tadi yang diberi label primitif.
Saya kira, dalam diskusi ini (bisa dilihat di posting2 sebelumnya), dalam urusan label primitif dan gambaran kondisi gaptek masyarakat, saya maupun Heru hampir (atau mungkin bahkan sudah) dalam 'frekuensi' yang sama.
Perbedaannya 'hanya' terletak pada pandangan dasar atas faktor penting pendukung kondisi gaptek yang, menurut saya, mempunyai implikasi terhadap visi, metoda dan strategi dalam menumbuhkan masyarakat melek teknologi.
Saya kira, wacana ini menjadi menarik dan perlu agar kelompok minoritas melek teknologi tidak terjebak ke dalam sikap solipstik dan lupa mengevaluasi diri jika memang berniat memperluas melek teknologi dalam masyarakat.
Heru:
walah,
lha kok jadi gini yah??
lha, jadinya malah "dihujat" ama Yayan & Adi yah?
Kalau saja ada kamera yang merekam proses saya menulis tanggapan-tanggapan untuk isu ini, Anda dapat melihat saya tersenyum dengan kepala dingin; dan ada secangkir kopi panas di meja yang membuat saya rileks. Sama sekali tak ada niat maupun suasana ingin menghujat atau berseteru dengan para aktivis milis ini.
Konyol sekali jika kita berniat berseteru di tengah situasi yang menuntut kerja bersama. Berbeda pandangan, OK. Berseteru, NO.
Barangkali pernah ada trauma di milis ini yang membuat setiap diskusi selalu diperlakukan sebagai sebuah perseteruan?
Don't worry, be happy.
Salam
Ternyata, email saya tersebut belum mengakhiri percakapan. Heru masih memberikan responnya. Dan saya pun meresponnya sebagai sebuah keterangan. Memang terasa aneh bahwa diskusi mengenai gagap teknologi di tengah komunitas melek teknologi berujung dengan percakapan semacam itu. Tapi apa boleh buat, faktanya memang demikian.Dan nampaknya, saya agak malas berdiskusi lagi jika berujung semacam ini. Berikut ini respon saya yang terakhir pada idskusi tersebut.
Ok Yayan,
mohon maaf kalau saya sampai salah kata,
saya gak bilang anda ngajak berseteru,
saya hanya -merasa- terhujat,
tapi ya itu.... bisa jadi perasaan saya yg "salah",
Saya kira, tak ada persoalan pribadi di diskusi ini (bahkan saya baru bertemu muka hanya dengan 2 atau 3 orang anggota milis ini saja). Juga tak ada alasan untuk menghujat siapapun dalam diskusi ini.
Percayalah, perasaan Anda "salah" dalam hal "terhujat". Setidaknya, saya tidak punya niat maupun motif untuk menghujat Anda.
Lagi pula, sejauh ini, bukankah diskusi kita itu lebih ke soal landasan berpikir dalam melihat fenomena gaptek dalam masyarakat kita? Tak ada sesuatu yang bersifat pribadi, saya kira.
kalau anda gak keberatan,
saya bermaksud menyampaikan sesuatu yg -mungkin- sensitif bagi anda,
menurut saya,
kalau anda dalam keadaan rileks saja sudah bisa mengeluarkan kalimat2
yg -menurut saya- agak vulgar, apalagi dalam keadaan emosional....
Vulgar? Mungkin bagi Heru kalimat saya itu vulgar. Tapi bagi yang lain, kalimat saya itu mungkin konyol dan bodoh -atau bahkan mungkin gak ada artinya sama sekali karena mungkin saya gagal menyusun kalimat yang komunikatif. Mungkin saja begitu.
Saya rasa, ini risiko yang jamak saja dalam komunikasi dengan banyak pihak yang punya latar belakang kultur yang berbeda. Apalagi kita berkomunikasi tanpa tatap muka. Jadi jamak saja jika serangkaian teks bisa menghasilkan nuansa yang bermacam-macam.
Dalam keadaan emosional? Saya juga tidak tahu bagaimana jadinya .... Tapi mudah-mudahan itu tak pernah akan terjadi.
atau,
benar bahwa pembawaan orang memang beragam,
Mungkin begitu. Pembawaan dan style orang memang beragam.
Ijinkan saya mengucapkan rangkaian kalimat sakti dalam bergaul:
"Mohon maaf jika ada yang terluka. Hanya berniat mau berdiskusi saja"
Sekali lagi,
don't worry, be happy
Salam