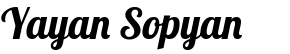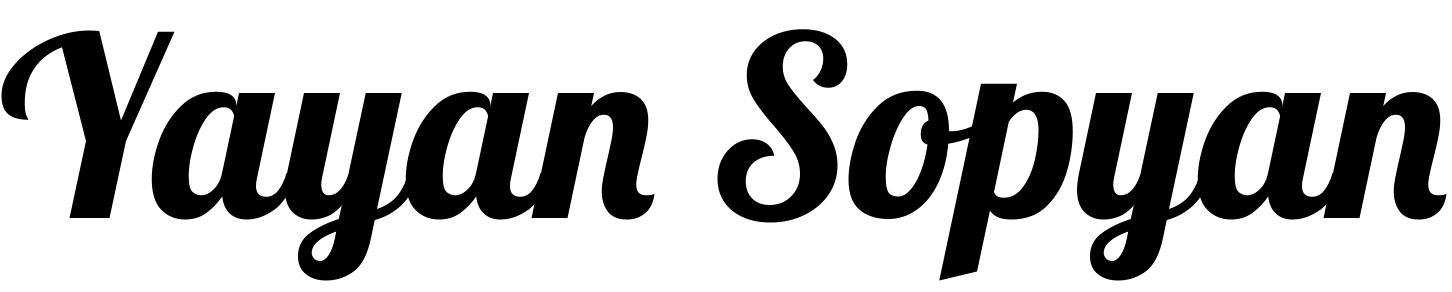11 Nopember 2002, Donny BU -ketua ICT Watch, yang saya kenal sejak menjadi wartawan detikcom- mengirimkan email. Saya tak dapat menceritakan email itu sebab -atas permintaan Donny- email itu dikategorikan sebagai "for your eyes only". Saya tentu menerima dan membalas email dengan senang hati.Sehari kemudian, Donny pun kemudian merespon balasan email saya itu. Topiknya sangat menarik. Tentang jurnalisme dan pemberitaan peristiwa aksi protes sejumlah hacktivis atas tindakan pemerintah Australia dalam menggeledah warga negara Indonesia sehubungan dengan propaganda anti-terorisme global. Tak ada titipan pesan "for your eyes only" pada email kali ini. Maka tak ada salahnya, obrolan kami dapat dinikmati lebih banyak orang. Siapa tahu bermanfaat.
Berikut ini tanggapan saya atas email Donny pada 12 Nopember 2002.
Tak Ada Jurnalisme Dasamuka
Donny bicara tentang kenetralan media, terutama dalam liputan konflik. Donny nampaknya sepakat dengan tengarai bahwa ada ketidaknetralan media dalam liputan berbagai peristiwa konflik. Aku mendapat kesan (dan mungkin aku salah membacanya) bahwa Donny memimpikan kenetralan media itu.
Pertanyaanku, sepanjang sejarah media, adakah kenetralan itu?
Aku ge er. Sebagai orang yang sudah menimba ilmu di bidang komunikasi pada tingkat yang cukup lanjut, Donny pasti sependapat dengan ku bahwa tak ada catatan sejarah tentang media yang benar-benar netral. Dan kenyataan ini bukan semata-mata karena dikehendaki oleh orang-orang media.
Struktur sosialitas manusia tidak memungkinkan seseorang untuk sungguh-sungguh netra. Struktur psikologi dan bilogi manusia juga tidak diciptakan untuk mendukung manusia untuk benar-benar netral.
Muka jurnalis itu hanya ada satu, dan dua matanya terletak di situ. Secara fisik ia tidak akan pernah mampu melihat segala sudut pada saat yang sama. Sang jurnalis, mau tidak mau, harus memilih sebuah sudut pandang terhadap sebuah peristiwa maupun fenomena.
Barangkali akan beda jika sang jurnalis punya 10 muka -dasamuka- yang memungkinkan ia mengambil 10 sudut pandang pada saat yang sama. Tapi kalaupun sang jurnalis punya 10 muka, rasanya problem netralitas tak juga bisa diselesaikan. Tak ada jaminan bahwa sebuah peritiwa atau fenomena dapat dilihat secara penuh dari 10 sudut pandang.
Secara psikologis, manusia normal tidak bisa melakukan konsentrasi terhadap lebih dari satu sudut pandang pada saat yang sama. Sistem operasi komputer terbaru bisa berjalan secara multi-tasking. Tapi komputer tak punya aspek psikologi.
Secara sosial, ingatan sosial seseorang -yang terbentuk oleh sosialitasnya sejak ia lahir- tak memungkinkan ia untuk menjadi makhluk yang tidak berpihak. Adakah manusia yang terbebas dari keberpihakannya secara sosial? Ketika seseorang mengambil sikap untuk "tidak berpihak" sekalipun maka ia sesungguhnya juga telah memilih keberpihakannya. Hidup memang paradoksal, Don.
Ada juga orang yang berpikir aneh, yang mengharapkan bahwa jurnalisme berjalan sedingin mesin perekam peristiwa. Apakah alat-alat bantu jurnalis juga bekerja netral secara total? Kamera hanya merekam peristiwa sejauh kejadian-kejadian berada dalam frame-nya. Microphone (bahkan yang bersifat omni sekalipun) hanya mewartakan peristiwa sejauh ia bisa menangkap gelombangnya. Artinya, bahkan alat-alat bantu kita pun secara struktural mendorong pemakainya untuk memilih sebuah sudut pandang.
Aku rasa, ini wacana yang sangat basic. Sangat gampang untuk mendapatkan rujukan-rujukan filsafat sosial, filsafat bahasa, atau semiotika yang menjadi dasar bagi ilmu komunikasi modern, yang akan memperlihatkan kepada kita betapa struktur sosial manusia tidak memungkinkan relasi yang netral antar orang. Ini salah satu hal yang disebut para filsuf fenomenologi sebagai situasi batas (grand situation) deterministik dalam relasi antar manusia.
Jurnalis akan menjadi salah satu orang yang selalu didesak untuk memilih satu sudut pandang dalam bekerja. Ia tak bisa digiring ke omong kosong tentang sikap netral total dan tidak berpihak. Jurnalisme dasamuka tak pernah ada.
Ah, kayaknya kita sudah sama-sama mengalami, wacana soal netralitas media hanya nikmat kita lakukan sewaktu penataran P4 saja. Tapi ketika kita sudah masuk ke perpustakaan dan bangku kuliah yang sesunguhnya (apalagi bekerja di bidang media), kita akan tertawa-tawa melihat kedunguan kita sendiri sewaktu ngotot-ngototan perkara kenetralan media.
Yang tersisa, menurut aku, adalah etika komunikasi; atau etika jurnalisme. Dan bukan semata-mata kode etik jurnalistik. Buat aku pribadi, pilarnya adalah fairness dan kejujuran. Bersikap fair dan jujur tidaklah berarti harus bersikap netral.
Rasanya aku gak perlu jelaskan lebih panjang mengenai perkara ini. Donny pasti sudah tahu kemana arahnya.
 Hacktivisme Bukan Perang Cyber
Hacktivisme Bukan Perang Cyber
Pada bagian lain email yang aku terima, Donny menulis, "saya meragukan apakah perang memang "confirmed" terjadi tanpa ada pernyataan dari pihak australia". Dan oleh karenanya pemeberitaan memgenai mass defacing, menurut Donny, belum cover both side.
Aku rasa, salah satu kesalahan awal pemetaan peristiwa yang dilakukan oleh jurnalis, narasumber, maupun para komentator pada peristiwa mass defacing ini adalah memposisikannya sebagai sebuah perang. Positioning ini telah menjerumuskan sekian banyak orang pada debat kusir yang memperebutkan pepesan kosong.
Peristiwa ini bukanlah peristiwa peperangan cyber. Peristiwa ini adalah peristiwa aksi protes para hacktivis.
Perang cyber hanya akan muncul sebagai bagian dari peperangan dua (atau lebih) negara. Tak ada perang cyber tanpa peperangan antar negara. Tak ada peperangan cyber dalam hacktivisme.
Seperti halnya dalam bentuk-bentuk aktivisme lain, para hacktivis hanya berkepentingan untuk unjuk rasa agar isu yang diusungnya mendapat perhatian publik dan mempengaruhi pengambil keputusan. Hacktivisme tidak berkepentingan untuk memancing serangan balasan menuju sebuah peperangan.
Jika ada yang berharap bakal muncul serangan balasan dari Australia, pertanyaan serangan balasannya itu ditujukan kesiapa? Ke si Tarjo?? Darjo? Ke si Fulan? Siapa itu Tarjo, darjo, Fulan? Dimana mereka? Apakah mereka punya properti yang bisa dijadikan sasaran serangan balasan?
Yang bener aja. Cara berpikirnya jadi lucu kan?
Ini bukan perang kok. Ini aksi protes kok. Jadi, buat apa menuntut konfirmasi tentang peperangan?
Sebagai pembaca berita, yang aku butuhkan sekarang bukanlah konfirmasi tentang peperangan. Yang penasaran pembaca ingin tahu saat ini adalah respon pemerintah Australia atas aksi protes ini. Apa responnya? Boleh jadi, responnya adalah "tidak merespon" yang menindikasikan bahwa aksi-aksi protes itu sejauh ini tidak mempengaruhi pengambilan keputusan mereka dalam propaganda anti-terorisme global. Dan itu boleh terjadi kan?
Hacktivisme: Berpolitik dalam kultur Internet
Diinspirasikan oleh sebuah film yang pernah ditonton, Donny mencoba membuat "kajian ringan" dengan membagi aksi para hacktivis Indonesia menjadi 3 proses: proses rekruitmen, proses kejadian dan ekspresi lanjutannya. Ini untuk memperlihatkan bahwa "pada awal hacker2 tersebut termotivasi melakukan hacking bisa jadi memang karena rasa patriotisme itu sendiri. tetapi ketika di medan pertempuran, tidak menutup kemungkinan ada faktor lain yang membuat mereka bertahan mati-matian atau menyerang habis-habisan, semisal ekspos media massa."
Kalau aku boleh berbahasa lugas, apa yang donny sebut sebagai "kajian ringan" itu lebih terlihat sebagai ilusi penonton film. Pada level tertentu, barangkali ilusi ini bisa di-gathuk-gathukan dalam melihat fenomena aktivisme offline. Tapi tidak bisa diterapkan untuk melihat hacktivisme atau bentuk-bentuk aktivisme bermediasikan komputer lainnya.
Hacktivisme sama sekali tidak mengenal recruitment. Dalam aktivisme bermediasikan komputer tak pernah ada proses dan pembentukan afiliasi politik secara formal seperti yang terjadi dalam aktivisme offline.
Kita tidak bisa menerapkan cara yang sama untuk memahami partisipasi dan komunikasi politik individu dalam gerakan semacam FPI atau Forkot (atau front lainnya di dunia offline) di satu sisi, dengan apa yang terjadi pada gerakan hacktivisme di sisi lain. Ini bukan soal perbedaan medium belaka. Melainkan juga karena lanskap kultur dan sosiologi politik keduanya mempunyai karakter yang berbeda.
Meski keduanya sama-sama merupakan gerakan langsung ekstraparlementer, namun karakteristiknya berbeda. Sebagai suatu gerakan sosial, hacktivisme lebih kental diwarnai oleh sifat indenpendensi masing-masing partisipannya baik secara indivudal maupun sebagai sebuah gerombolan. Tak ada ikatan yang kuat diantara para partisipan. Teknologi internet telah membangun sebuah kultur komunitas yang anggota-anggotanya sangat independen dan cair (fenomena semacam ini agak sudah ditemukan sbelum era Internet).
Satu-satunya hal yang dapat mengikat para partisipan dalam gerakan sosial akar rumpun Net adalah isu-nya. Sementara metoda maupun tujuannya, hanya masing-masing partisipan yang tahu dan berhak memilih sendiri. Dan itu sah-sah saja dalam kultur cyber yang memungkinkan individu untuk independent dan mentrasformasikan diri ke dalam bentuk apapun sesuai dengan pengetahuan, kemampuan, kemauannya masing-masing.
Hacktivisme, pertama-tama, harus dipahami juga sebagai suatu gerakan sosial akar rumput. Gerakan ini tidak memerlukan otoritas sosial politik dari lembaga-lembaga formal manapun. Karena merupakan hasil konvergensi sub-kultur hacker, membuat para hacktivis termasuk dalam kelompok yang akan menisbikan segala petatah petitih standar norma sosial yang berlaku di dunia offline.
Mungkin ada satu dua sejarah gerakan sosial akar rumput yang memper-memper seperti hacktivisme. Gerakan sosial akar rumput generasi bunga (hippies) tahun 60-an di Amerika barangkali agak memper-memper dengan hacktivisme (bahkan mungkin ada hacktivis yang diinspirasikan oleh gerakan generasi bunga ini). Tapi secara keseluruhan, juga tak benar-benar sama.
Jadi, meminjam gaya anak Medan, "Ini kultur cyber, bung!" Mencoba menjelaskan fenomena cyber dengan cara menjabarkan fenomena non cyber (atau bahkan dengan ilusi), hanya akan membuat kita tambah terperosok dan berhalusinasi.
Terjerumusnya sekian banyak anak muda kedalam dunia carding adalah buah pahit yang harus kita petik dari cara kita yang salah dalam memahami kultur Internet. Apakah kita akan mengulangi kesalahan yang sama di bidang kultur politik internet?
Yang Kita Butuhkan: Peta Baru Kebudayaan
Tentang penjelasan "simbiosme mutualisme" yang Donny sampaikan, aku tak perlu berkomentar banyak. Sebab tidak ada yang spesial untuk didiskusikan mengenai penjalasan tersebut. Itu hanya teori mekanisme interaksi media dan masyarakatnya yang biasa saja, yang pada prakteknya lebih dikendalikan oleh politik keredaksian masing-masing publisher. Dan kita tahu, tak ada keyakinan dan sikap politik keradaksian yang boleh dianggap sebagai norma umum. Masing-masing punya pilihan dan boleh diperdebatkan oleh masing-masing ideolognya, tentu.
Aku lebih tertarik untuk menantikan sebuah penyikapan yang relevan terhadap kultur Internet, yang di sini sangat terabaikan karena ternyata kita sangat miskin wawasan dalam mengapresiasi kultur baru ini.
Kemiskinan ini memang merupakan risiko yang harus kita tanggung sebagai akibat dari kedunguan kita dalam mengapresiasi teknologi. Entah dimana ahli-ahli komunikasi, politik, para filsuf, ahli semiotika, sosiolog kita berada dalam mengapresiasi era teknologi ini. Kemiskinan dan keterbelakangan teknis selama ini rupanya telah membuat kebanyakan anggota masyarakat kita menjadi kelompok besar orang yang minder, dan oleh karenanya akan selalu tunduk pada kelompok kecil masyarakat yang menguasai teknik dan perdagangan teknologi.
Para jurnalis, misalnya, akan selalu menempatkan persoalan Internet sebagai melulu persoalan TI, persoalan teknis. Ini jadi blunder karena beberapa hal. Pertama, kebanyakan jurnalis tidak mampu menangkap penjelasan teknis. Kedua, banyak pakar TI tidak mampu berkomunikasi dengan baik sehingga seringkali penjelasannya tak sampai ke otak jurnalis. Ketiga, jurnalis dan pakar TI tidak mampu melihat dengan jernih aspek-aspek sosial, kultur, dan politik dari Internet.
Tak ada salahnya dengan kelompok kecil masyarakat teknik dan perdagangan teknologi ini. Bahkan kita boleh berbangga. Tapi ketika cara kita mengapresiasi internet melulu dari sisi teknik dan perdagangan maka yang terjadi adalah sebuah proses reduksi yang tidak memungkinkan kita membuat peta kebudayaan baru yang jelas, yang membuat masyarakat kita siap berada di dalamnya.
Selama ini, apa yang kita hasilkan hanyalah kelahiran priyayi-priyayi baru dalam masyarakat gaptek. Tak ada capaian teknologi yang terekspos. Tak ada gelagat kesiapan budaya kita menghadapi kultur baru Internet. Bahkan, yang menyedihkan, yang muncul malah intrik-intrik yang tidak bermutu.
Aku dengar, Donny sangat berminat pada Computer Mediated Communication (CMC). Buat aku, ini sangat menggembirakan. Masyarakat kita sedang membutuhkan para ahli baru di bidang ini untuk dapat memberikan peta baru paradigma komunikasi di era Internet.
Tapi, kepakaran di bidang ini rasanya tak mungkin bisa dicapai selama kita masih memegang paradigma lama komunikasi dan sosiologi. Berbagai rujukan mutakhir tentang studi CMC jauh lebih banyak ketimbang 7 tahun lalu -ketika aku pertamakali mengenal Internet. Tapi rujukan-rujukan itu tidak bermanfaat jika kita masih cukup resisten terhadap paradigma-pradigma baru dan masih tergoda untuk menjadi bagian dari kelompok priyayi baru dalam masyarakat gaptek kita.
Salam
Yayan Sopyan