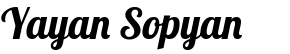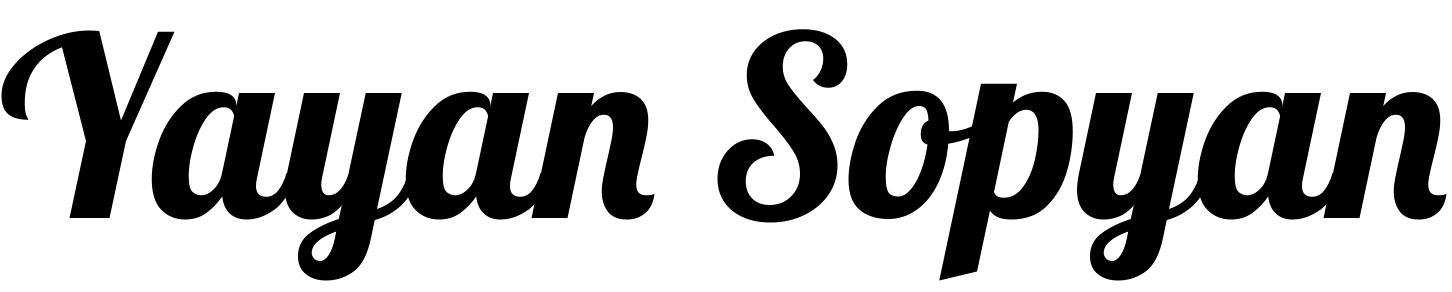Seorang pejabat tinggi Amerika Serikat tanpa sengaja menambahkan Jeffrey Goldberg, editor majalah The Atlantic, ke dalam percakapan rahasia antarpejabat di aplikasi Signal. Yang dibahas bukan agenda remeh, melainkan rencana serangan militer terhadap kelompok Houthi di Yaman.
Dalam hitungan menit, ruang virtual yang didesain sebagai saluran komunikasi aman itu berubah menjadi kamar bolong yang memalukan. Peristiwa ini, yang kemudian dikenal sebagai Signalgate, membuka selubung persoalan yang lebih dalam: teknologi modern bisa memberi rasa aman yang semu dan menyuburkan praktik pemerintahan bayangan yang tak terpantau publik.
Signal, aplikasi perpesanan yang dikenal berkat sistem enkripsinya, memang dirancang untuk menjamin privasi. Tapi seperti yang dibuktikan oleh Signalgate, teknologi sekuat apa pun tak bisa menyelamatkan kita dari kesalahan manusia. Kelalaian kecil—seperti salah menambahkan anggota grup—membuka akses pada informasi strategis yang semestinya tertutup rapat.
Dalam konteks militer, ini bukan cuma soal reputasi, tapi menyangkut keamanan nasional, kredibilitas diplomatik, dan potensi korban jiwa. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, semua ini terjadi di luar saluran komunikasi para pejabat resmi pemerintahan, tanpa jejak arsip, tanpa prosedur audit, tanpa pertanggungjawaban.
Ketika para pejabat pemerintah mulai mempercayakan proses pengambilan keputusan di atas platform privat seperti Signal, mereka sebenarnya sedang melakukan tindakan yang sangat gegabah. Enkripsi memang melindungi dari penyadapan eksternal, tapi tidak dari kekeliruan internal. Apalagi, sebagian besar aplikasi seperti Signal didesain untuk konsumen biasa, bukan untuk mengelola rahasia negara.
Di sinilah letak masalahnya: terlalu banyak kepercayaan diberikan pada alat, terlalu sedikit perhatian pada sistem dan manusianya. Dalam suasana yang mendesak dan penuh tekanan, pejabat bisa tergoda untuk mencari jalur komunikasi yang cepat, padahal jalur itu belum tentu aman atau akuntabel secara institusional.
Skandal Signalgate bukan cuma soal lemahnya keamanan teknologi, tapi juga tentang ketidakwaspadaan dan kegegabahan penggunanya. Skandal ini juga memperlihatkan bahwa teknologi bisa memberi jalan ke sebuah ranah gelap pengelolaan negara: shadow governance.
Ketika pembahasan isu-isu strategis para pejabat negara dipindahkan ke ruang-ruang privat yang tak terjangkau hukum dan pengawasan publik, kita tidak lagi bicara soal efisiensi. Kita bicara soal kekuasaan yang berjalan tanpa pengawasan, tanpa rekam jejak, dan tanpa batas institusional. Shadow governance bukan berarti konspirasi, tapi sebuah pola: keputusan besar dibuat secara informal, oleh segelintir orang, di luar sistem yang semestinya mengikat mereka.
Dalam kasus Signalgate, percakapan tentang operasi militer tidak pernah melewati prosedur dokumentasi formal. Tidak ada notulen, tidak ada arsip, tidak ada jejak. Dan ketika ada kesalahan, tidak ada yang bisa dimintai tanggung jawab secara sah.
Di era digital, praktik seperti ini bisa berkembang subur karena teknologi memfasilitasi privasi personal dengan sangat baik—bahkan terlalu baik. Aplikasi seperti Signal atau Telegram menawarkan fitur disappearing messages, enkripsi end-to-end, dan kontrol akses yang sulit dilacak.
Dalam kehidupan pribadi, ini mungkin dibutuhkan. Tapi ketika fitur-fitur tersebut dipakai oleh pejabat negara untuk urusan kenegaraan, yang muncul adalah ketegangan antara dua prinsip dasar: privasi dan transparansi. Pemerintah membutuhkan ruang diskusi yang aman, tapi publik juga berhak tahu bagaimana keputusan diambil—terutama keputusan yang berpotensi menimbulkan perang.
Lebih jauh lagi, Signalgate menjadi peringatan penting bagi negara-negara dengan demokrasi semu—yang secara institusional terlihat demokratis, tapi dalam praktiknya dikuasai oleh elite terbatas, oleh oligark. Di tempat-tempat seperti ini, praktik shadow governance bisa tumbuh diam-diam lewat jalur digital.
Tapi justru karena sering kali tidak terlindungi secara optimal, para hacktivist berpeluang membongkar lapisan-lapisan rahasia ini. Para hacktivist, yang berfokus kepada pembocoran kongkalingkong dan persekongkolan busuk elite politik maupun kalangan oligark, bisa memberikan perhatian khusus kepada fenomena shadow governance yang memanfaatkan teknologi.
Kita memang butuh teknologi yang aman. Tapi lebih dari itu, kita butuh tata kelola yang jernih dan manusia yang bijak dalam memakainya.
Signalgate mengingatkan kita bahwa komunikasi yang terenkripsi kadang justru jadi selubung bagi kekuasaan yang ingin bersembunyi. Di sanalah shadow governance bisa bertumbuh. Skandal ini bukan cuma tentang satu aplikasi atau satu kebocoran, tapi tentang bagaimana kita, sebagai masyarakat digital, memilih mengelola kekuasaan, teknologi, dan tanggung jawab publik.
Yang paling berbahaya bukan teknologi itu sendiri, tapi ketika kekuasaan merasa tak perlu lagi dilihat oleh mata publik.