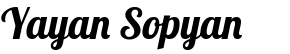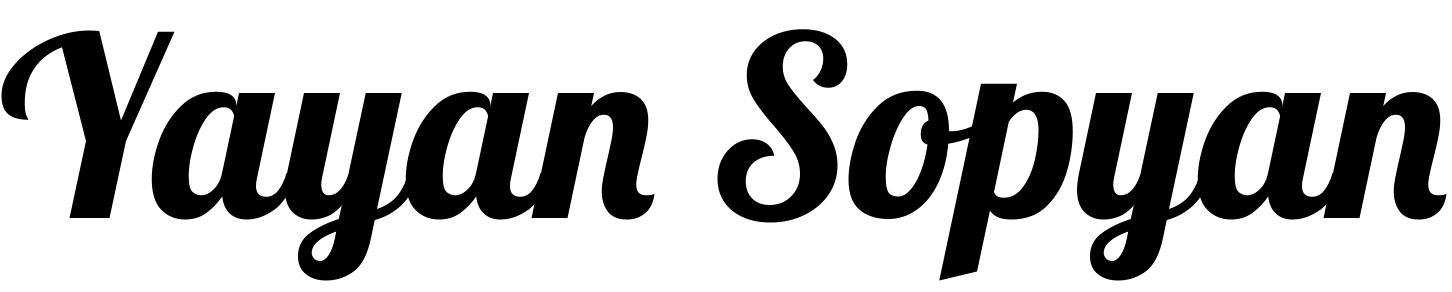Kebanyakan penulis butuh ketenangan dalam bekerja? Saya percaya, itu betul.
Namun apa benar penulis bekerja dengan senyap? Saya tidak yakin itu.
Seorang jurnalis lebih sering menulis cerita liputannya di ruangan yang sama dengan jurnalis-jurnalis lain yang juga sedang menulis kisah hasil liputan masing-masing dengan kebisingan tertentu. Banyak penulis yang saya kenal memutar musik selama mereka bekerja.
Saya juga tidak menghindari kebisingan ambient tertentu ketika menulis; bahkan sering membutuhkannya. Kebisingan kafe, terutama.
Saya pernah mengira suasananyalah yang membuat saya betah dan lebih produktif jika menulis di kafe. Rupanya, bukan suasana kafe yang membuat saya merasa lebih nyaman dan produktif menulis, melainkan bebunyian ambient-nya yang membuat saya menyukai tempat itu.
Suara desis mesin kopi, denting piring dan cangkir beradu, dan suara percakapan orang yang tak terlalu jelas terdengar di kafe itu, menurut penelitian, tergolong kebisingan ambient tingkat sedang -sekitar 70 dB. Itu bukan suara yang bisa disebut tenang, apalagi senyap; tapi juga bukan kebisingan tingkat tinggi yang bisa melukai (85 dB). Meskipun begitu, gangguan yang dihasilkan oleh kebisingan tingkat sedang seperti ambient kafe itu, menurut peneliti, justru mendorong orang berpikir lebih imajinatif. Kebisingan kafe itu merangsang konsentrasi dan kreativitas.
Tentu saja saya tidak harus ke kafe untuk menulis. Jika membutuhkan kebisingan kreatif seperti itu, saya tetap bisa menikmatinya di kamar kerja saya: giling dan seduh kopi, lalu putar rekaman ambient kafe yang sudah saya download dari Internet sebelumnya. Saya tetap bisa mendapat aroma kopi dan ambient kafe meski bekerja di kamar sendiri.
Bukan cuma dalam proses menulis naskah, dalam proses mengedit naskah pun, penulis sebaiknya mencoba “kebisingan” lain. Yang saya maksud, bukan kebisingan ambient; melainkan membaca lantang naskah yang sedang diedit.
Ketimbang membacanya dalam hati tanpa suara, cobalah membaca naskah yang sedang anda edit secara lantang. Ketika membaca naskah dengan lantang, ada proses yang terasa melambat sehingga membuat kita bisa lebih fokus dan cermat memeriksa naskah itu.
Seorang penulis akan selalu mengedit naskahnya berulang-ulang untuk memastikan naskahnya sudah layak untuk disuguhkan ke pembaca dan tidak mengandung kesalahan. Pada saat naskah itu dibaca berulang-ulang tanpa suara, selalu ada risiko bahwa ia silap mata. Ada kesalahan-kesalahan yang terlewatkan dan terabaikan.
Silap mata itu bisa terjadi karena seorang penulis merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling tahu kandungan naskah yang sedang diedit. Karena tidak ada suara lain selain asumsi tersebut di otaknya, penulis cenderung tidak cukup waspada ketika membaca naskahnya di dalam hati tanpa suara.
Lain hasilnya jika naskah itu dibaca dengan suara lantang oleh si penulis. Suara lantang yang ia dengar sendiri membuat ia berposisi seperti orang lain yang sedang membaca naskahnya. Dengan begitu si penulis didorong untuk membandingkan apa yang ia dengar dengan apa yang ia maksudkan.
Dalam proses itulah penulis mungkin menemukan kesalahan atau kebutuhan untuk memperbaiki naskahnya. Bukan hanya soal kesalahan tulis (typo), tapi juga menyangkut banyak aspek yang perlu diperiksa selama proses mengedit seperti alur cerita, alur informasi atau alur argumen, pengulangan yang tidak diperlukan, ungkapan yang canggung atau terasa norak, dan lainnya.
Membaca dengan suara lantang memang butuh tenaga tambahan dibandingkan dengan membaca dalam hati tanpa suara. Terlebih jika naskah yang perlu dibaca itu adalah naskah buku yang tebal.
Untuk membaca lantang naskah yang sedang saya edit, saya memakai fitur Red Aloud yang ada di menu Review Microsoft Word. Itu sangat membantu saya untuk lebih waspada ketika mengedit. Dengan cara itu saya lebih mudah untuk waspada, menemukan kata atau kalimat yang tidak pas, transisi antar paragraf yang tidak mulus dalam naskah saya, tanpa mengganggu mulut saya yang mungkin sedang asik dengan kopi dan keripik singkong.