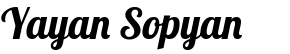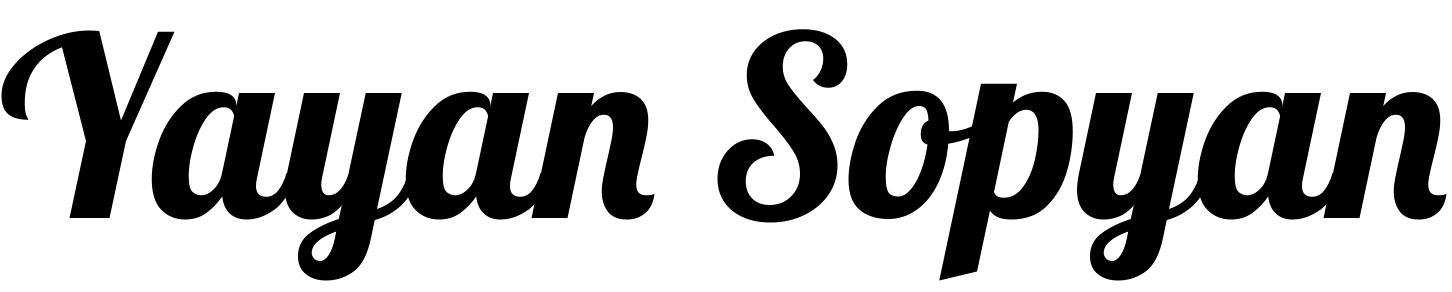Sekarang batas antara pekerja dan pengguna semakin kabur. Sebuah aplikasi yang diunduh di ponsel bisa menjadi tempat seseorang bekerja, berjejaring, dan membangun eksistensi. Orang bisa menjadi produsen tanpa menyadarinya, menciptakan nilai tanpa kompensasi, dan berkontribusi pada ekonomi tanpa pernah merasa sebagai bagian darinya. Semakin banyak individu yang menggantungkan hidupnya pada platform digital, tetapi semakin sedikit yang menyadari betapa terbatasnya kendali mereka atas ruang tempat mereka beroperasi.
Kondisi ini mengingatkan pada konsep alienasi dalam teori Marx. Dulu, keterasingan pekerja berasal dari pemisahan mereka dengan produk yang mereka buat. Seorang buruh pabrik mungkin menghabiskan harinya membuat barang yang tidak pernah mereka miliki, bekerja dengan cara yang tidak bisa mereka atur, dan berkompetisi dengan buruh lain yang seharusnya menjadi sekutu mereka.
Hari ini situasinya lebih kompleks. Bukan cuma pekerja di pabrik yang teralienasi, tetapi juga mereka yang mengisi internet dengan konten, data, dan tenaga kerja digital.
Seorang kreator konten menghabiskan waktu berjam-jam membuat video di platform yang bukan miliknya, cuma untuk algoritma yang berubah tanpa pemberitahuan. Seorang pekerja gig menerima pesanan lewat aplikasi yang menentukan tarif tanpa melibatkan mereka dalam negosiasi. Seorang pengguna media sosial membangun jaringan, berbagi pemikiran, dan menulis pengalaman hidup, tetapi semua data itu disimpan dan dimonetisasi oleh perusahaan yang tidak mereka kenal. Mereka bekerja, tetapi bukan pekerja. Mereka menciptakan, tetapi bukan pemilik.
Ekonomi digital tidak sekadar mengubah hubungan sosial, tetapi mengacak batas-batas lama yang dulu terasa jelas. Dulu, pemodal, pekerja, dan konsumen memiliki peran yang cukup terpisah. Sekarang, seseorang bisa berada di ketiganya sekaligus tanpa menyadarinya.
Seorang pengguna media sosial adalah konsumen dari iklan yang muncul di feed-nya, tetapi juga produsen dari setiap klik, like, dan komentar yang menjadi bahan analisis data bagi platform. Seorang pekerja lepas di ekonomi gig adalah buruh yang bergantung pada aplikasi, tetapi sekaligus pemilik usaha kecil yang harus memasarkan dirinya sendiri. Peran-peran ini terus bergeser, menciptakan bentuk keterasingan yang tidak selalu terlihat.
Kaum Kiri Baru pernah memperingatkan bahwa alienasi di masyarakat industri tidak cuma berasal dari hubungan produksi, tetapi juga dari budaya dan psikologi. Dalam dunia yang didominasi oleh algoritma dan kapitalisme platform, keterasingan bukan lagi sekadar kehilangan kendali atas pekerjaan, tetapi juga atas identitas, data, dan kehidupan sosial kita.
Orang-orang bekerja tanpa merasakan makna kerja itu sendiri, menciptakan nilai tanpa menerima bagian yang sepadan, dan membangun hubungan sosial di ruang yang dikendalikan oleh pemodal besar. Apa yang dulu dianggap sebagai kebebasan individu—kemampuan untuk bekerja kapan saja, menjadi kreator tanpa perantara, atau membangun bisnis sendiri—ternyata justru menciptakan eksploitasi dalam bentuk baru.
Tentu, ekonomi digital bukan cuma tentang eksploitasi. Ada kemungkinan bahwa teknologi membuka jalan bagi hubungan sosial yang lebih kaya, kolaborasi yang lebih luas, dan akses terhadap peluang yang lebih besar. Internet memungkinkan seseorang berbicara dengan audiens global, membangun komunitas berbasis solidaritas, dan menemukan bentuk ekspresi yang tidak tersedia di dunia fisik.
Tetapi semua ini berlangsung dalam kerangka yang dikendalikan oleh pemodal besar. Platform bukan cuma tempat interaksi, tetapi juga alat akumulasi modal. Setiap klik, unggahan, dan transaksi memperkuat kontrol perusahaan atas data dan kebiasaan pengguna.
Kepemilikan atas ruang digital menjadi pertanyaan mendasar. Kalau internet telah menjadi infrastruktur sosial utama, bagaimana mungkin kita membiarkan ruang ini dimonopoli oleh segelintir perusahaan? Apakah kita masih bisa menyebutnya ruang publik kalau segala gerak di dalamnya ditentukan oleh kepentingan pemodal?
Kalau pekerjaan manusia semakin bergantung pada algoritma, apakah para pekerja seharusnya tidak memiliki suara dalam cara algoritma itu bekerja? Kalau ekonomi digital memungkinkan eksploitasi tenaga kerja secara terselubung, apakah ada alternatif yang lebih adil?
Pertanyaan-pertanyaan itu bisa jadi masih akan terus berubah, mengikuti dinamika teknologi yang bergerak lebih cepat daripada kesadaran kita untuk memahami dampaknya. Tapi satu hal yang pasti: dunia digital bukan sekadar tempat kita berinteraksi, mencari nafkah, atau berekspresi. Ini adalah ruang tempat kekuasaan didistribusikan, dikonsentrasikan, atau direbut kembali.
Bagi mereka yang cuma melihat internet sebagai kemudahan, mungkin ini bukan persoalan besar. Tapi bagi mereka yang menggantungkan hidup pada algoritma, yang bekerja dalam sistem yang mereka tidak kuasai, yang harus beradaptasi setiap kali aturan main berubah tanpa peringatan, ini bukan sekadar perkembangan teknologi. Ini adalah penguasaan atas cara hidup itu sendiri.
Sewaktu kita membuka aplikasi, mengunggah konten, atau bekerja dalam ekonomi digital, pertanyaannya bukan lagi apakah kita pekerja atau pengguna. Kita selalu keduanya sekaligus. Yang lebih penting untuk ditanyakan adalah: dalam sistem yang tak pernah kita rancang ini, apakah kita masih punya hak untuk menentukan bagaimana permainan ini dimainkan?
Esai ini terbit pertama kali di Arina.id