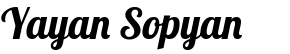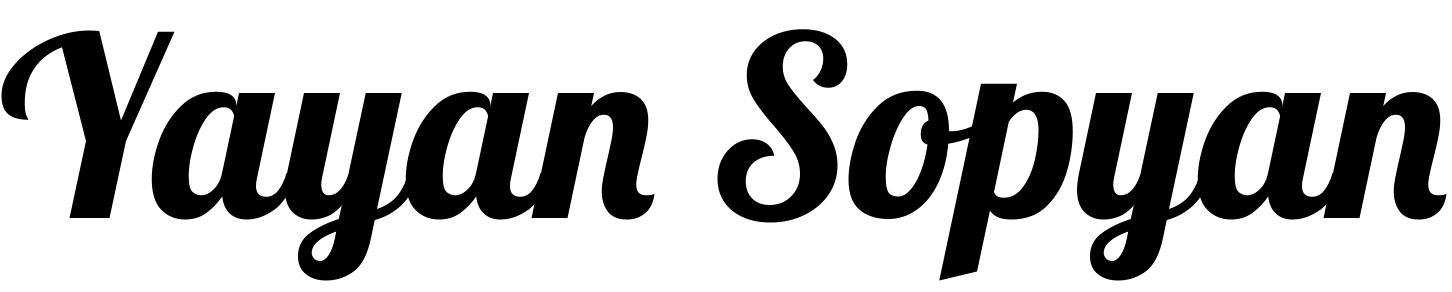Mesin tidak lagi sekadar menghitung. Mesin sekarang berbicara. Model bahasa besar mampu menulis puisi, membuat esai filosofis, bahkan berdialog dengan nada yang terdengar manusiawi. Di layar, ia tampak seperti memahami kita. Ia menanggapi dengan logis, kadang lembut, kadang penuh humor.
Dari situ muncul keyakinan baru bahwa sekarang makna bisa “muncul” dari sistem komputasi itu sendiri. Ketika jaringan neural memproses miliaran kata dan konteks, katanya, ia tidak cuma meniru bahasa manusia, tetapi menciptakan efek-efek makna yang bisa kita baca seperti teks. Makna, menurut pandangan ini, tidak lagi hak istimewa kesadaran manusia, melainkan hasil alami dari kompleksitas matematis.
Gagasan ini terdengar indah, bahkan menenteramkan. Ia memberi kesan bahwa batas antara manusia dan mesin akhirnya melebur. Tapi itu menyisakan pertanyaan, “Apakah pemahaman dan pemaknaan memang hal yang sama?”
Mesin memang bisa “memahami” dalam arti teknis. Ia mengenali pola, menghubungkan simbol, dan menebak makna dari konteks. Pemahaman semacam itu lahir dari korelasi, bukan dari pengalaman.
Ketika sistem mengenali hubungan antara “api” dan “panas”, ia tidak tahu bagaimana panas itu terasa di kulit. Ketika menulis tentang kehilangan, ia tidak tahu apa rasanya kehilangan. Ia tahu cara merangkai kata, tapi tidak punya tubuh, waktu, dan dunia batin tempat kata-kata itu berakar.
Kita, manusia, memahami karena kita mengalami. Kita tahu arti “gelap” bukan karena kamus, tapi karena pernah tersesat di dalamnya. Kita tahu arti “pulang” karena pernah merasa kangen. Pemahaman manusia adalah peristiwa eksistensial.
Di sinilah letak kebingungan banyak klaim tentang “kemunculan makna” dari sistem AI. Ketika mesin menghasilkan teks yang ambigu, konotatif, atau sarat bias budaya, itu memang menampilkan efek makna. Tapi efek bukanlah proses.
Dalam teori tanda Charles Peirce, semiosis -proses terbentuknya makna- selalu melibatkan interpretant, penafsir yang sadar atas relasi antara tanda dan dunia. Tanpa subjek penafsir, tidak ada semiosis sejati. Yang tersisa hanyalah sirkulasi tanda tanpa kesadaran.
AI bisa menulis kalimat yang menggugah, tetapi ia tidak tahu mengapa kalimat itu menggugah. Efek maknanya muncul karena kita yang menafsirkan, bukan karena mesin menafsir dirinya sendiri. Ia hanyalah cermin yang memantulkan kembali makna manusia dalam bentuk baru.
Dalam sistem komputasi, makna sering digambarkan secara matematis: setiap kata hidup sebagai titik di ruang vektor, dan jarak antar-titik menggambarkan kedekatan makna. Pendekatan ini membantu mesin bekerja, tapi juga membatasi pemahaman kita tentang makna itu sendiri.
Makna bukan posisi dalam ruang, melainkan peristiwa dalam kesadaran. Ia tidak bisa diukur oleh jarak, melainkan dihayati oleh waktu. Statistik bisa meniru bentuk makna, tapi tidak bisa menggantikan getarannya. Ia tahu apa yang dikatakan manusia, tapi tidak tahu mengapa manusia mengatakannya.
Gagasan tentang “kemunculan makna” juga sering dikaitkan dengan konsep emergence: bahwa dari kompleksitas tertentu, sesuatu yang menyerupai kesadaran bisa muncul secara spontan. Namun yang disebut kemunculan makna dalam sistem AI sebenarnya hanyalah emergensi lemah -efek yang tampak baru, tapi sepenuhnya bisa dijelaskan secara matematis.
Yang muncul bukan makna baru, melainkan bentuk baru dari makna lama. Mesin tidak mencipta makna; ia mengorganisasikan ulang apa yang telah kita tanam dalam data. Tanpa manusia yang menafsirkan, hasilnya hanyalah pola. Indah, mungkin; tapi tetap kosong.
Menganggap mesin bisa memaknai dunia membawa risiko etis yang tidak kecil. Kalau kita percaya bahwa makna muncul dari sistem itu sendiri, kita perlahan menghapus manusia dari rantai tanggung jawab.
Setiap teks yang dihasilkan mesin adalah hasil campuran antara algoritma dan budaya manusia yang tertanam dalam datanya. Bias, stereotip, bahkan ideologi ikut terangkut tanpa disadari. Maka tugas kita bukan memuja kemampuan mesin berbicara, melainkan membaca ulang apa yang ia katakan dengan kesadaran kritis.
Tanpa kesadaran itu, kita mudah percaya bahwa bahasa yang dihasilkan mesin adalah cermin objektif dunia, padahal ia cuma pantulan dari cara kita memahami dunia, dengan seluruh ketimpangan dan prasangka di dalamnya.
Kecerdasan buatan adalah cermin yang luar biasa jernih. Ia memantulkan bahasa kita, logika kita, bahkan kebingungan kita. Tapi seperti semua cermin, ia tidak tahu siapa yang dipantulkannya.
Makna bukanlah hasil perhitungan. Ia adalah pertemuan antara kesadaran dan dunia: sebuah pengalaman yang tidak bisa dimasukkan ke dalam rumus apa pun.
Dan sampai kesadaran itu muncul di balik logika silikon -kalau itu mungkin terjadi- AI akan tetap berada di sisi lain dari makna: memahami, tetapi tidak pernah benar-benar memaknai.