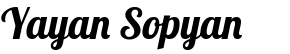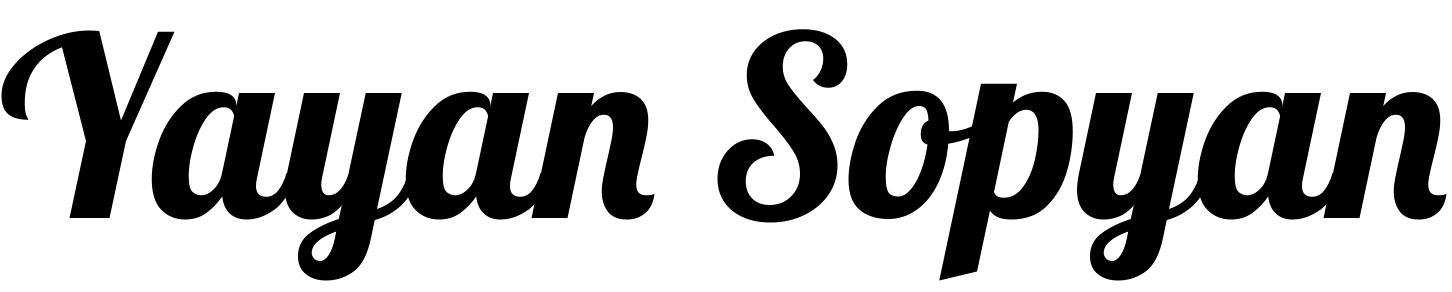Hari ini, siapa saja bisa membangun cerita tentang brand-nya. Bahkan mereka yang tidak pernah menulis sebelumnya. Kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI) telah membuka jalan bagi pemilik usaha -baik besar maupun kecil, pekerja lepas, bahkan brand personal untuk menyusun narasi yang terdengar profesional, emosional, dan menggugah dalam hitungan detik.
AI memberi banyak kemudahan: cukup satu perintah sederhana, kemudian mesin akan menulis kisah yang tampak hangat dan jujur tentang bagaimana brand itu dimulai, nilai apa yang dipegang, dan untuk siapa ia hadir.
Seorang penjual kue rumahan, misalnya, bisa meminta ChatGPT membuat narasi menyentuh tentang kenangan masa kecilnya bersama ibunya yang dulu suka membuat kue. Seorang konsultan muda bisa dengan cepat membuat deskripsi personal yang menjelaskan mengapa ia memilih jalur independen sebagai profesional. Bahkan, dengan AI, versi cerita itu bisa disesuaikan: satu untuk audiens di LinkedIn, satu lagi untuk media sosial lain yang lebih kasual, atau untuk profil di laman web.
Semua terdengar manusiawi. Tapi semua juga bisa dihasilkan oleh mesin.
Pertanyaannya, apakah cerita-cerita itu sungguh mencerminkan siapa brand itu? Atau cuma membungkus impresi agar terlihat lebih bermakna?
Pertanyaan-pertanyaan itu menggiring kita ke pertanyaan dasar: apa itu brand story sebenarnya?
Brand story adalah cara sebuah brand menyatakan siapa dirinya, mengapa ia ada, dan nilai apa yang ingin ia bawa ke dunia. Cerita ini bisa berbentuk narasi asal-usul, pengalaman personal, atau bahkan refleksi dari kegagalan dan proses bangkit. Brand story yang jernih tidak cuma menjawab pertanyaan “apa yang kami jual?”, tapi “kenapa kami memilih jalan ini?”
Di era AI, makna brand story mulai bergeser. Teknologi ini membawa potensi besar untuk mentransformasi brand story menjadi strategi naratif yang terpersonalisasi, efisien, dan bisa diproduksi massal. Cerita bisa disesuaikan untuk tiap segmen audiens, ditulis dalam berbagai gaya bahasa, bahkan dipetakan berdasarkan respons emosi dari data interaksi pengguna.
Begini, misalnya, sebuah brand perawatan kulit bisa menyajikan tiga versi narasi kepada tiga jenis audiens: satu ditulis dengan gaya percaya diri untuk perempuan muda yang aktif, satu dengan nada menenangkan untuk ibu yang kelelahan, dan satu lagi dengan pendekatan ilmiah untuk pria yang skeptis.
Semua ditulis dalam hitungan detik. Semua tampak menyentuh. Tapi pertanyaannya tetap sama: cerita ini punya siapa? Narasi yang lahir dari mesin mungkin terdengar jujur, tapi apakah ia sungguh jujur? Cerita yang menyentuh mungkin memancing empati, tapi apakah empati itu diarahkan pada pengalaman nyata atau ilusi yang dibuat untuk memikat?
Ada juga kecenderungan lain yang mulai tampak: pengalaman manusia yang nyata -seperti kisah pelanggan, komunitas, atau individu- diekstrak lalu diolah ulang oleh AI agar lebih dramatis, lebih memikat, lebih layak dibagikan. Kadang tanpa izin, atau tanpa menyertakan konteks.
Apa bedanya hal itu dengan eksploitasi cerita? Bukankah itu tidak menghormati tubuh dan pengalaman hidup yang mengalaminya?
Sementara itu, perusahaan besar dengan sumber daya AI yang canggih bisa terlihat sangat “manusiawi” dalam narasinya, padahal semua disusun berdasarkan perhitungan. Di sisi lain, brand kecil yang benar-benar lahir dari peluh dan harapan nyaris tidak terdengar karena narasinya dianggap “kurang halus”, “kurang engaging”, atau “kurang algoritmis”. Di sinilah cerita tidak lagi menjadi jembatan antara manusia dan makna, tapi alat untuk memenangkan perhatian -apa pun risikonya.
Yang kita butuhkan sekarang bukan lagi kecanggihan baru, tapi kesadaran baru. Bahwa brand story seharusnya bukan sekadar strategi persuasi, tapi ekspresi niat. Cerita bukan cuma tentang bagaimana kita bicara, tapi mengapa kita bicara. Dan kepada siapa kita bicara.
AI bisa membantu menyusun kalimat, memperhalus gaya, atau menyusun kerangka. Tapi ia tidak bisa memutuskan apakah cerita ini layak diceritakan. Ia tidak bisa merasakan beban makna di balik kalimat “kami memulai dari nol.” Ia tidak tahu bagaimana luka, harapan, atau keyakinan dibentuk dari pilihan-pilihan sulit.
Karena itu, kita perlu membangun etika baru dalam bercerita -sebuah kerangka moral yang menempatkan manusia sebagai pusat, bukan cuma sebagai target. Kita perlu bertanya, sebelum menerbitkan sebuah cerita: apakah ini mencerminkan nilai yang kita yakini? Apakah ini mengangkat, bukan mengeksploitasi? Apakah ini akan tetap layak dibaca lima tahun dari sekarang, ketika hype telah hilang?
Di era AI, kita bisa membuat cerita yang menyentuh hati tanpa pernah menyentuh kehidupan nyata. Tapi brand yang memilih jalan lambat, jujur, dan manusiawi—mungkin akan tertinggal dalam jumlah klik, tapi akan bertahan lebih lama dalam ingatan dan kepercayaan.
Dan itu, barangkali, adalah satu-satunya cerita yang layak diceritakan.