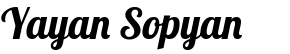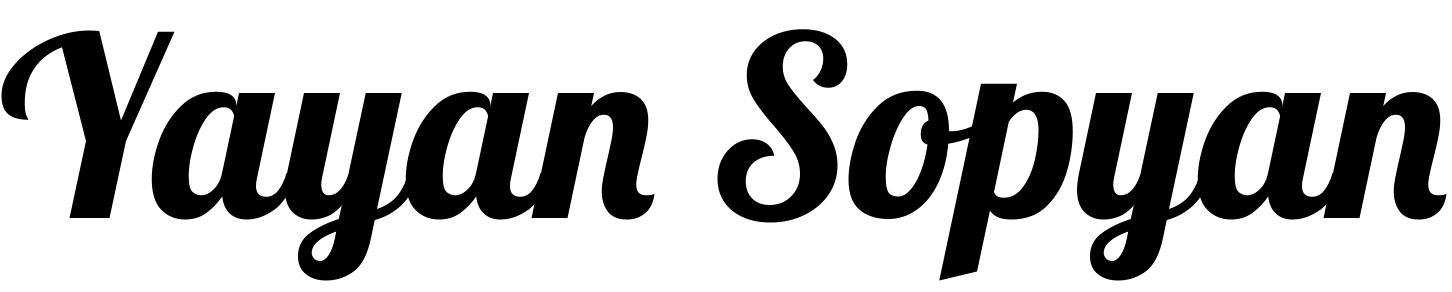Apakah Anda memakai GenAI seperti ChatGPT dalam kerja di organisasi atau perusahaan? Kalau iya, apakah organisasi atau perusahaan tempat Anda bekerja mempunyai panduan dan policy penggunaan articial intelligence (AI) untuk keperluan bekerja? Kalau organisasi atau perusahaan tidak punya keduanya, apakah Anda tetap memakai ChatGPT atau sejenisnya untuk urusan pekerjaan secara diam-diam?
Di banyak kantor hari ini, sesuatu terjadi diam-diam. Seorang staf keuangan menyalin data ke ChatGPT untuk dibuatkan narasi laporan. Seorang analis minta ringkasan riset lewat AI. Seorang manajer bertanya soal tren terbaru pada chatbot sebelum meeting penting.
Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mencatat. Inilah yang disebut shadow AI—penggunaan kecerdasan buatan tanpa sepengetahuan atau persetujuan resmi dari organisasi.
Sekilas, ini tampak seperti taktik bertahan dalam dunia kerja yang makin cepat dan menekan. AI menjadi semacam asisten virtual yang bekerja tanpa gaji, tanpa istirahat, tanpa mengeluh. Tapi di balik kepraktisan itu, ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih penting: cara kita membentuk dan memahami pengetahuan sedang berubah secara diam-diam.
Selama ini kita terbiasa menganggap pengetahuan sebagai sesuatu yang bisa disusun dan disimpan: dalam bentuk laporan, presentasi, ringkasan, atau data. Cuma saja, pengetahuan tidak pernah sesederhana itu. Ia tidak lahir dari hasil cetakan, melainkan dari proses—dari pertanyaan yang jujur, dari diskusi yang berlapis, dari keraguan yang menuntun pada pemahaman. Pengetahuan bukan hasil instan, melainkan sesuatu yang tumbuh dan diuji lewat berpikir bersama.
Shadow AI memotong jalur proses ini. Ia menghasilkan sesuatu yang tampak rapi dan meyakinkan, tapi bisa jadi tanpa konteks. Tanpa keterlibatan manusia yang sesungguhnya.
Saat seseorang membawa laporan yang disusun sepenuhnya oleh AI, tanpa benar-benar memahami cara kesimpulannya dibentuk, apa yang sebenarnya dibagikan? Hasil, ya. Tapi apakah itu pengetahuan?
Saya beri satu contoh gambaran. Satu tim kerja mengambil keputusan penting. Masing-masing anggota tim membawa dokumen yang dibantu AI—diam-diam. Tak ada yang tahu sejauh mana AI berperan dalam penyusunan ide atau narasi. Mereka berdiskusi seolah semua informasi itu hasil pemikiran mereka sendiri. Tapi tidak ada proses kolektif. Tidak ada pemahaman bersama. Cuma tumpukan jawaban yang tidak bisa ditelusuri jejak berpikirnya.
Kita mungkin punya data, grafik, dan narasi yang meyakinkan. Tapi kita kehilangan jejak: siapa yang menyusunnya, apa pertimbangan yang dipakai, dan di mana titik-titik keraguannya. Saat proses berpikir tidak lagi terlihat, pengetahuan kehilangan fondasinya.
Salah satu fondasi penting itu adalah agensi—kemampuan dan tanggung jawab manusia untuk memilih, memahami, dan menjelaskan. Shadow AI mengikis agensi karena ia menggantikan proses tanpa bisa dimintai pertanggungjawaban.
Kita bisa menyalahkan laporan yang keliru, tapi siapa yang akan menjelaskan cara berpikir di baliknya? AI tidak bisa diminta berdiri dalam rapat untuk menjawab kritik. Dan saat kita terlalu sering bergantung padanya, kita mulai kehilangan kehadiran kita sendiri dalam proses berpikir.
Sebagian orang mungkin berpikir, “Kalau begitu, jadikan saja AI resmi di organisasi. Beri pelatihan. Buat aturannya. Biarkan semua orang memakainya secara terbuka.”
Nyatanya, tidak sesederhana itu. Keterbukaan tidak otomatis melahirkan pemahaman. Kalau budaya kerja tetap mengejar hasil cepat dan mengabaikan proses, maka AI yang legal pun tetap menggantikan berpikir, bukan mendukungnya.
Maka pertanyaan yang lebih penting bukanlah “AI-nya sembunyi-sembunyi atau terbuka?”, melainkan, “Apakah cara kita memakai AI mendekatkan kita pada pemahaman, atau justru menjauhkan kita darinya?”
Organisasi yang bijak bukan sekadar menyediakan akses pada alat canggih, melainkan menciptakan ruang berpikir yang sehat. Yaitu, tempat orang bisa menjelaskan bagaimana mereka berpikir, sejauh mana AI membantu, dan bagaimana hasilnya dipahami bersama.
AI bisa membantu banyak hal. Ia bisa menyusun draft awal, memetakan alternatif, atau menyarankan sudut pandang baru. Tapi tetap harus ada manusia yang menyaring, mengoreksi, memberi konteks, dan—yang paling penting—bertanggung jawab.
Pengetahuan tidak tumbuh dari hasil copy paste yang rapi. Ia tumbuh dari percakapan, dari pertanyaan yang belum selesai, dari proses yang bisa dilacak dan dikritisi bersama. Dan proses itu harus tetap menjadi milik manusia.
Shadow AI sedang menguji kita. Bukan cuma sebagai profesional, tapi sebagai manusia yang berpikir. Apakah kita masih menghargai proses belajar, memahami, dan menyusun makna? Atau kita mulai puas menjadi penonton dari jawaban-jawaban yang kita sendiri tak tahu bagaimana ia dilahirkan?
Pengetahuan bukan sekadar apa yang kita ketik atau tampilkan di layar. Ia adalah cerminan dari cara kita hadir—sebagai manusia yang berpikir, yang tidak menyerahkan akalnya pada mesin.