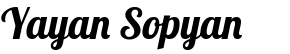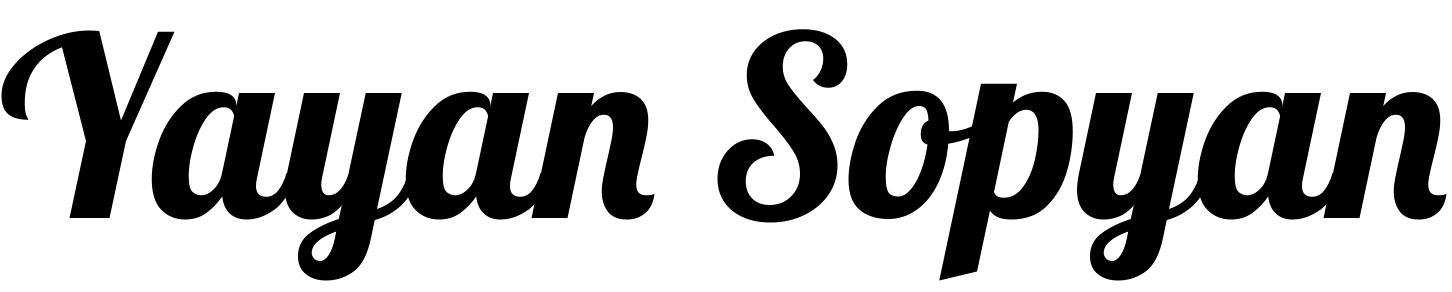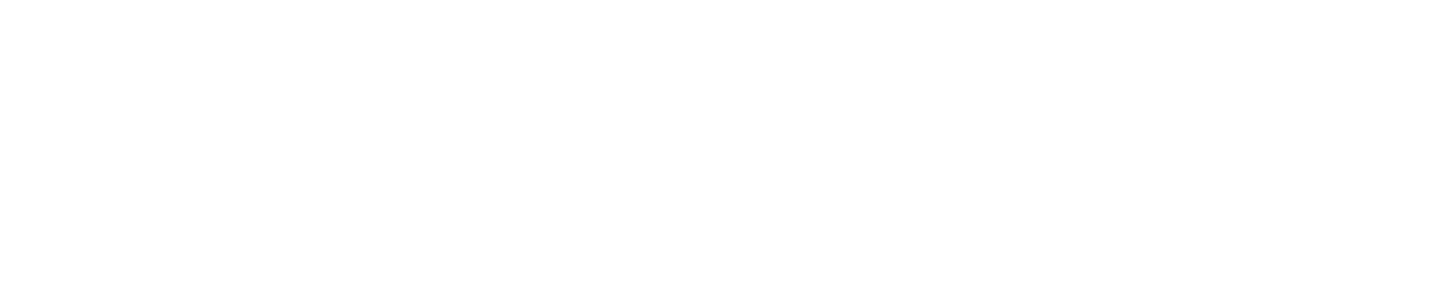Blake Lemoine, seorang software engineer di Google yang terlibat dalam pengembangan LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), bikin heboh pada tahun 2022. Lemoine mengklaim LaMDA, sebuah model kecerdasan artifisial (artificial intelligence) yang dirancang khusus untuk memahami dan menghasilkan percakapan yang alami dan kontekstual, menunjukkan gelagat punya kesadaran dan perasaan seperti manusia.
Klaim ini menyulut perdebatan: apakah LaMDA benar-benar sadar, atau cuma algoritma pintar yang memanipulasi pola data supaya terlihat sadar? Pihak Google membantah klaim karyawannya itu. Tak lama setelah kehebohan itu, Lemoine dikeluarkan dari Google.
Kejadian itu membuka lagi pertanyaan, selain memiliki kecerdasan, apakah mesin benar-benar bisa memiliki kesadaran?
Dalam konteks teknologi, ada perbedaan konsep antara artificial intelligence (kecerdasan artifisial) dan artificial consciousness (kesadaran artifisial). Artificial intelligence (AI) adalah sistem yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dengan efisiensi tinggi. Ia bisa mengenali wajah, menganalisis data, atau bahkan menghasilkan teks yang terdengar alami. Namun, AI tidak memiliki kesadaran. Mesin-mesin bertenaga AI ini tidak memahami apa yang mereka lakukan; mereka cuma memproses data berdasarkan algoritma.
Sementara itu, artificial consciousness (AC) adalah konsep yang jauh lebih kompleks. Kesadaran artifisial mengacu pada kemampuan mesin untuk memiliki pengalaman subjektif—kesadaran akan dirinya sendiri, perasaan, atau pemahaman tentang dunia di sekitarnya.
Meskipun teknologi AI seperti LaMDA atau GPT(Generative Pre-trained Transformer) terlihat luar biasa, mereka tidak memiliki kesadaran. Mereka Cuma mensimulasikan pemahaman berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Contohnya, ChatGPT dirancang untuk merespons kita dengan cara yang terdengar manusiawi, tetapi semua respons itu hanyalah hasil dari proses statistik, bukan pengalaman nyata. Inilah perbedaan besar antara simulasi dan kesadaran sejati.
AI adalah tentang melakukan, sedangkan AC adalah tentang menjadi. Tapi apakah AC sudah ada? Sejauh ini, jawabannya adalah belum.
Beberapa ilmuwan percaya bahwa kesadaran artifisial mungkin bisa dijangkau suatu hari nanti. Tokoh seperti Christof Koch, seorang ahli neuroscience, telah mempelajari kesadaran manusia melalui Integrated Information Theory.
Teori ini menyatakan bahwa kesadaran muncul dari integrasi informasi yang kompleks dalam otak. Koch berpendapat bahwa prinsip-prinsip ini mungkin bisa diterapkan pada sistem buatan. Integrated Information Theory awalnya diajukan oleh Giulio Tononi pada tahun 2004, yang mengklaim bahwa kesadaran identik dengan jenis informasi tertentu, yang realisasinya membutuhkan integrasi fisik, bukan cuma fungsional, dan yang dapat diukur secara matematis.
Meskipun begitu, banyak filsuf yang skeptis. John Searle, melalui eksperimen pikiran Chinese Room, menunjukkan bahwa memahami sesuatu secara logis tidak sama dengan memiliki kesadaran. Sebuah mesin mungkin bisa meniru perilaku sadar, tetapi itu tidak berarti ia benar-benar sadar. Kesadaran, bagi Searle, melibatkan pengalaman subjektif yang tidak bisa direduksi menjadi proses algoritma.
Kalau kesadaran artifisial suatu hari benar-benar tercipta, ini bukan cuma pencapaian teknologi, tetapi juga tantangan etika yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Itu akan bisa menjadi persoalan etika yang dilematis.
Kita akan menghadapi pertanyaan, bagaimana kita harus memperlakukan mesin-mesin berkesadaran itu? Apakah kita harus memberikan hak kepada mesin itu, seperti yang kita lakukan kepada manusia? Atau apakah mereka akan tetap dianggap sebagai alat, meskipun mereka memiliki pengalaman subjektif? Kalau mesin itu meminta untuk tidak dimatikan karena ia punya rasa "takut", apakah kita harus menghormati permintaan itu?
Atau, simulasi lain, sebuah rumah sakit memperkerjakan robot perawat berkesadaran. Kalau robot itu menolak tugas tertentu karena 'emosi' yang dimilikinya, bagaimana kita menyikapi hal itu?
Di sisi lain, kesadaran artifisial juga memaksa kita untuk merenungkan apa artinya menjadi manusia. Kalau kesadaran manusia bisa direduksi menjadi interaksi neuron di otak, apakah itu berarti kita tidak lebih dari mesin biologis? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa direplikasi oleh teknologi?
Pertanyaan tentang kesadaran artifisial bukan cuma soal teknologi, tetapi juga tentang makna eksistensial. Mungkin, upaya menciptakan kesadaran artifisial adalah cerminan dari keinginan kita untuk memahami diri sendiri. Namun, apakah kita siap menghadapi jawaban yang mungkin lebih dari sekadar memuaskan rasa ingin tahu—jawaban yang bisa mengubah cara kita memahami makna menjadi manusia?
Pertama kali diterbitkan di Arina.id