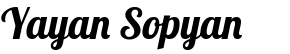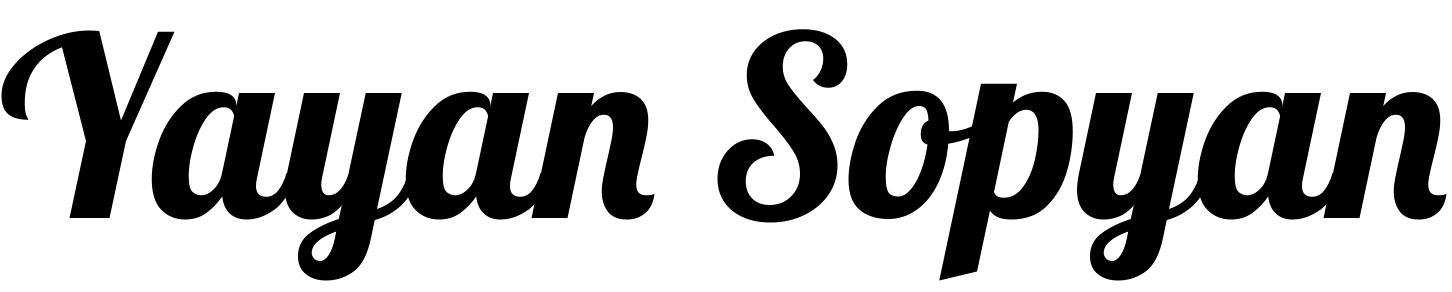Sejak beberapa waktu lalu, media sosial dibanjiri gambar-gambar bergaya Studio Ghibli. Ada yang berupa versi animasi dari potret diri, foto keluarga, atau sekadar foto kucing peliharaan.
Tidak berhenti di ranah personal, banyak pula gambar yang bersumber dari peristiwa sejarah, potret tokoh publik, adegan politik, bahkan potongan film layar lebar. Semuanya diolah dalam estetika khas Studio Ghibli: warna-warna lembut, latar yang tenang, dan nuansa dongeng yang akrab.
Tren ini menyusul peluncuran fitur image generator baru dari ChatGPT, yang memungkinkan siapa pun mengubah gambar biasa menjadi ilustrasi bergaya Ghibli—dan juga banyak gaya lainnya—dalam hitungan detik.
Di Indonesia, tren ini bertepatan dengan suasana Lebaran. Banyak keluarga mengubah foto mereka menjadi gambar bergaya Ghibli sebagai kartu ucapan yang menyenangkan untuk dibagikan.
Pertanyaannya: mengapa kemampuan artificial intelligence (AI) untuk mengubah gambar menjadi gaya Ghibli ini begitu menggoda?
Dalam hitungan jam setelah fitur ini diumumkan, tercatat ada satu juta pengguna baru yang mendaftar ke ChatGPT. Angka yang mengesankan, apalagi kalau kita bandingkan dengan tren lain yang tak kalah canggih secara teknologi.
Sebab faktanya, dunia AI saat ini penuh dengan penawaran visual yang jauh lebih liar dan eksploratif. Pengguna Facebook, misalnya, bisa “menyuruh” Meta AI membuat gambar seekor kucing berkacamata mengendarai mobil balap. Imajinasi semacam itu bisa diwujudkan dengan mudah, dan tampilannya juga memukau. Tapi tampaknya justru bukan imajinasi liar seperti itu yang menarik perhatian luas.
Kita juga tidak bisa buru-buru menyimpulkan bahwa tren ini cuma didorong oleh fandom terhadap Studio Ghibli. Banyak pengguna bahkan bisa jadi tidak tahu siapa Hayao Miyazaki—seniman manga yang juga salah satu pendiri Studio Ghibli—atau belum pernah menonton My Neighbor Totoro. Tapi mereka tetap merasa gambar-gambar itu “hangat,” “tenang,” atau “menyenangkan.”
Memang harus diakui, estetika Ghibli punya kekuatan visual yang khas. Ia tidak bekerja lewat kejutan atau dramatisasi, melainkan lewat kelembutan, ritme yang pelan, dan perasaan yang ditanamkan dengan hati-hati. Langit biru, rumput hijau, cahaya sore di teras rumah—semuanya bukan adegan besar, tapi justru karena itu terasa manusiawi. Ia menyentuh sesuatu yang dalam dan akrab, tanpa perlu dikenali lewat nama.
Namun bukan cuma estetika yang membuat tren ini menyebar begitu cepat. Cobalah lihat apa yang dipilih orang untuk divisualisasikan.
Mereka tidak membuat gambar-gambar liar atau fantasi yang sepenuhnya tak terbayangkan. Mereka tidak membayangkan dunia alternatif, planet asing, atau makhluk ajaib. Justru yang paling sering dipilih adalah hal-hal yang sudah dikenal: foto keluarga, suasana rumah, tempat bersejarah, tokoh publik, hingga meme yang sedang viral. Semuanya berasal dari dunia nyata—dari pengalaman yang punya versi faktual dalam ingatan.
Di sinilah letak benang merahnya. AI image generator ini memang membuka ruang bagi imajinasi, tapi bukan imajinasi yang tercerabut dari kenyataan. Ia justru berakar kuat pada hal-hal yang dekat, yang dikenali, yang pernah kita alami, lihat, atau hayati. Ketika gambar-gambar itu diolah menjadi versi Ghibli, yang tercipta bukan dunia baru, melainkan pengalaman ulang atas dunia yang sama—dengan rasa yang berbeda.
Ketika gaya ini ditempelkan pada momen sejarah atau foto politik, ia tidak menghapus bobot fakta. Sebaliknya, ia memberikan cara pandang baru yang lebih personal. Ketegangan bisa terasa lebih tenang, kesedihan menjadi lebih bisa dihadapi, dan kegembiraan menjadi lebih hangat. Ini bukan soal menyederhanakan kenyataan, tapi mempertemukan kenyataan dengan kelembutan.
Barangkali, dalam fenomena ini tersembunyi sesuatu yang lebih dalam: hasrat manusia untuk melembutkan dunia.
Dunia kita hari ini penuh dengan kabar buruk, konflik, dan kebisingan. Bahkan potongan kenangan yang menyenangkan pun kadang terasa datar dalam bentuk aslinya. Ketika teknologi memberi cara untuk mengubah itu semua menjadi visual yang hangat dan bisa dirasakan ulang, orang akan menyambutnya dengan antusias.
AI, dalam konteks ini, bukan cuma alat yang canggih. Ia tidak sekadar menciptakan ulang bentuk, tetapi memberi lapisan emosi baru pada apa yang sudah kita kenal. Kita bisa melihat ulang sejarah, momen keluarga, atau potongan budaya populer—dan merasa ada sesuatu yang berubah dalam cara kita mengingatnya.
Fenomena ini memberi isyarat penting: penerimaan terhadap teknologi tidak selalu ditentukan oleh kehebatannya, tetapi oleh sejauh mana ia menyentuh hal-hal yang sudah dekat dalam hidup kita.
AI yang bisa menjawab semua pertanyaan mungkin membuat kagum, tapi AI yang bisa mengubah foto keluarga menjadi sesuatu yang menghangatkan hati—itulah yang membuat kita ingin menyimpannya, membagikannya, bahkan merasakannya kembali.
Itu sebabnya wajar kalau tren ini begitu cepat menyebar. Ia memberi pengalaman emosional yang cepat dan menyenangkan, tanpa perlu pengantar teknis atau referensi budaya khusus. Ia bekerja dengan cara yang sederhana: mengambil yang kita kenal, lalu memperlihatkannya dalam bentuk yang lebih indah, lebih lembut, dan lebih bersentuhan.
Mungkin tren ini akan berlalu. Tapi ia meninggalkan jejak bahwa dalam lautan kemungkinan yang ditawarkan AI, banyak orang justru memilih untuk kembali ke sesuatu yang sudah mereka tahu—bukan untuk mengulang, tapi untuk merasakan ulang.
Dan di tangan teknologi yang punya sentuhan estetika, bahkan potongan kecil dari kenyataan bisa menjadi tempat pulang yang tak terduga.