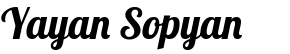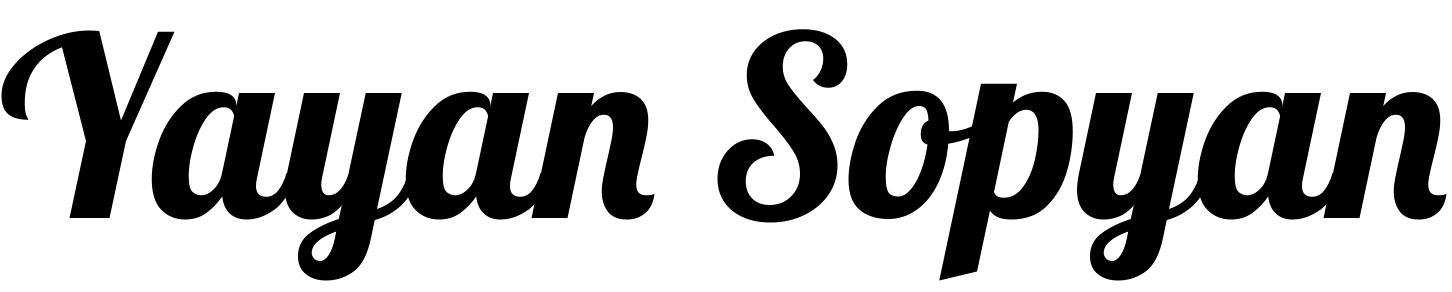Semakin sering kita berbicara tentang AI, semakin sering juga kita mendengar kalimat yang membuat mesin terdengar seperti punya kehidupan. Kita bilang AI “mengerti”, “memutuskan”, “cenderung ke sana”, “merasa begini”.
Awalnya, itu terasa sepele, karena memang begitu cara kita berbahasa. Kita memberi karakter kepada benda yang tidak bernyawa, dan itu terasa wajar.
Urusannya jadi lain ketika kebiasaan itu dibawa ke soal teknologi yang sekarang masuk ke ruang kekuasaan. Ada sesuatu yang berubah. Kita mulai memperlakukan algoritma bukan sebagai alat, melainkan sebagai sosok yang punya kehendak.
Di situlah masalahnya bermula: kita menggeser batas antara yang hidup dan yang tidak.
AI memang bisa menyusun kalimat yang rapi, mengutip teori, memprediksi pola, atau menawarkan solusi. Semua itu membuat kita mudah mengira bahwa ia “mengerti”.
Padahal, AI tidak punya pengalaman apapun untuk setiap hal yang disajikannya kepada kita. Tidak ada tubuh yang pernah menggigil ketakutan. Tidak ada napas yang terengah-engah di situasi genting. Tidak ada kehilangan yang pernah dirasakan. Tidak ada jejak hidup. Yang ada, cuma perhitungan yang berjalan dengan disiplin tinggi, tanpa emosi, tanpa konteks personal, tanpa sesuatu yang dipertaruhkan.
Sementara itu, kebijaksanaan manusia -yang sering kita sebut intuisi- lahir dari hal-hal yang justru sangat manusiawi: penyesalan, rasa bersalah, keberanian yang datang di situasi yang rapuh, atau keputusan yang kita ambil setelah menanggung konsekuensi dari keputusan sebelumnya. Ketika kita menyamakan intuisi dengan komputasi, kita kehilangan perbedaan yang paling mendasar: manusia membuat keputusan dengan seluruh dirinya, bukan sekadar dengan otaknya.
Narasi publik sering bergerak ke arah sebaliknya. AI diposisikan sebagai pihak yang lebih bersih ketimbang manusia. Tidak bisa disuap, tidak punya kepentingan pribadi, tidak terikat jaringan pertemanan, dan seterusnya. Seakan-akan begitu kita menyerahkan banyak urusan pada algoritma, persoalan moral yang terkandung di dalamnya juga akan ikut terselesaikan. Padahal persoalan moral tidak pernah berhenti di logika; ia berhenti pada seseorang yang mau bertanggung jawab atas dampak keputusan itu.
Ini yang sering terlupakan: AI tidak pernah memutuskan apa pun dengan sendirinya. Yang memilih data adalah manusia. Yang mengatur parameter adalah manusia. Yang menentukan di mana AI dipasang, untuk tujuan apa, dan siapa yang mengawasinya, juga manusia. Ketika kita mengatakan “AI memilih ini”, kita sedang menyederhanakan proses yang sesungguhnya penuh keputusan manusia di belakangnya.
Jadi, pertanyaan yang perlu diajukan itu bukanlah “apa yang akan dilakukan AI kepada kita”, melainkan “siapa yang menaruh AI di sana, dengan desain seperti apa, dan siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi kesalahan?”. Menggeser pertanyaan ini membuat seluruh percakapan tentang AI menjadi lebih jernih. Kita tidak lagi memikirkan AI sebagai makhluk baru yang hidup, melainkan sebagai alat yang bisa dipakai secara bijaksana atau sembrono.
Ada satu bahaya yang sering luput: ketika AI diberi panggung sebagai “wajah baru” pemerintahan atau organisasi, manusia yang seharusnya bertanggung jawab pelan-pelan bisa menghilang dari sorotan. Keputusan yang tidak populer bisa didorong kepada “rekomendasi sistem”. Ketidakadilan bisa dijelaskan sebagai “hasil algoritma”. Kegagalan bisa dibungkus sebagai “bug teknis”. Tanpa kita sadari, ruang untuk menggugat menjadi berkurang, karena subjeknya bergeser dari manusia ke mesin -padahal mesin tidak bisa kita mintai pertanggungjawaban.
Yang benar-benar menentukan arah teknologi tetaplah struktur politik, perusahaan yang menyediakan infrastrukturnya, dan orang-orang yang mengoperasikannya. Ketika kita terlalu sibuk menilai “sosok AI” di permukaan, kita mudah lupa melihat tangan-tangan yang bekerja di balik layar: siapa yang mengendalikan akses, siapa yang mendapat keuntungan, dan siapa yang bisa berhenti kapan saja ketika terjadi masalah.
Berhentilah mempersonifikasikan teknologi, dan mulailah melihatnya apa adanya: seperangkat alat yang harus dikelola, bukan sosok yang perlu diwaspadai atau dipuja. AI tidak pernah mempunyai air mata, dan mungkin tidak akan pernah. Itu bukan kelemahan; itu fakta dasar. Yang menjadi masalah adalah ketika kita menyerahkan urusan yang membutuhkan empati pada sesuatu yang memang tidak punya kemampuan itu, lalu terkejut ketika keputusan yang keluar terasa dingin.
Di sinilah kedewasaan dalam bercerita menjadi penting. Cara kita berbicara tentang mesin akan mempengaruhi cara kita memahami peran manusia. Semakin sering kita menghidup-hidupkan AI, semakin mudah pula kita melepaskan tanggung jawab. Sebaliknya, semakin tegas kita menjaga batas kategori -mana manusia, mana alat- semakin mudah kita memastikan bahwa teknologi bekerja untuk kita, bukan menggantikan ruang yang seharusnya tetap milik manusia.